Ibu
Ia bersiap-siap untuk kemah bersama teman
lamanya. Tas gunungnya terisi penuh dengan barang bawaan. Tak lupa kamera
SLRnya yang sudah full terisi baterai juga dibawanya. Beberapa bungkus
mie ditaruh di dalam tas, pakaian secukupnya, dan jaket tebal yang terpasang di
badan tinggi idealnya.
“Makan
dulu, Nak!”
Di sela
kesibukannya menata pakaian, ia acuh terhadap suara itu seolah-olah berkemas
lebih penting dan tidak ada lagi waktu selain detik itu.
“Makan
dulu, Nak!”
Suara
itu terdengar untuk yang kedua kalinya. Ia jawab dengan hembusan udara dari
dalam tenggorokannya. Tangannya sibuk memilah-milih pakaian. Di meja makan
sana, sang ibu menata piring dan menuangkan nasi. Kerap kali ia membuang muka
ke arah belakang, menutup mulutnya dengan sapu tangan dan batuk. Setelah
nasinya sudah siap, ia menghampiri anaknya di kamar dan menyibak gorden pintu.
“Ayo,
Nak, nasinya sudah siap.”
Sang
anak sedang asyik menerima telpon dari temannya. Tangan kanannya sibuk memegang
handphone. Suara dalam disertai batuk-batuknya semakin jauh di telinga
sang anak. Sang ibu menunggu sesaat berharap anaknya cepat memutus telpon.
Penelpon malah terbahak-bahak seperti memperbincangkan sesuatu yang seru, lebih
penting dari suara ibunya. Ia mendekati daun jendela, melihat jam dinding dan
kembali tertawa-tawa. Sang ibu dengan langkah super pelannya kembali ke meja
makan, terduduk menunggui anaknya. Ia menuangkan tempe ke piring dan mengisi
gelas dengan air bening.
Sang ibu
masih termenung. Mulutnya lirih melantunkan shalawat walau batuk menyerangnya.
Lama ia menunggu, sang anak tak kunjung datang.
Ia
keluar dari kamarnya lengkap dengan tas gunung di punggungnya.
“Bagas,
makan dulu, Nak!”
Sang ibu
berhasil menarik tangannya. Tangan gagah Bagas luluh dengan sentuhan tangan
sang ibu. Ia tak tega melepaskan pegangan erat tangan ibunya yang lemah. Bagaspun
terduduk dengan muka kusut menyimpan marah. Nasi dan lauk di depannya tak
menggairahkan nafsu makannya. Sang ibu menyodorkan masakan yang sudah
disiapkannya. Bagas mulai menyuapi mulutnya dengan sesendok nasi.
“Tempenya
tidak dimakan, Nak?”
Sang ibu
dengan lembutnya menawari masakan spesialnya. Walaupun tempe, tapi sang ibu
pandai meraciknya dengan bumbu bacem yang aromanya menggiurkan setiap hidung.
Namun tidak untuk anaknya yang kini menginjak remaja. Sang ibu sudah lama tak
melihat senyum riangnya ketika sang ibu menyuapinya makan dengan tempe. Bagas
kecil sangat menyukai masakan ibunya. Ia sering menggado tempe racikan ibunya.
Entah apa yang membuatnya berubah. Meski demikian, sang ibu tetap lemah lembut
dan sepenuh hati melayani anaknya.
“Ini,
Nak, ibu tambahkan lauknya.”
Bagas
mengelak tawarannya.
“Sudah,
Mak, Bagas sudah kenyang.”
Iapun
menggayang makanannya lalu minum.
“Nak,
cuacanya dingin ya?”
“Tidak,
Mak, biasa saja.”
“Tapi
Emak merasa kedinginan begini ya?”
“Itu
Emaknya saja yang kurang istirahat.”
Dalam
benaknya, sang ibu yang sudah menginjak usia senja mengharapkan pelukan hangat
anaknya. Namun ia tak sampai hati meminta anaknya untuk menghentikan acaranya
pergi main ke luar rumah bersama teman-temannya. Hanya ungkapan itu yang
terucap di mulutnya.
Guntur
mengetuk-ngetuk langit. Awan merembet mendung, pucat. Butiran-butiran bujan
mulai menghentak-hentak genting rumah. Bagas panik.
“Tuh,
kan. Ini semua gara-gara Emak.”
Sang ibu
terhenyak dengan suara keras anaknya. Mukanya terkejut penuh tanya.
“Apa
salah Emak? Ohok..”
“Coba
kalau Bagas gak makan dulu, pasti sudah berangkat dan sampai dari tadi. Makanannya
gak enak lagi.” Bagas berdiri dan menyingkirkan sepiring nasinya yang hampir
habis.
Hati
sang ibu tersungkur jatuh mendengar perkataan anaknya. Tidak ada sama sekali
niatan sang ibu untuk mengelak anaknya main. Ia hanya ingin makan bersama dan
memastikan perut anaknya sudah terisi makanan sekira membuat badannya kuat. Itu
saja.
“Maafkan
ibu, Nak. Besok ibu masak yang lebih enak lagi untuk Bagas.”
Sang ibu
berdiri menenangkan emosi anaknya, mengelus-ngelus punggungnya hingga ia
kembali terduduk. Meskipun hal itu tak membuat mulutnya merekah tersenyum, namun
setidaknya sang ibu telah mengalah dan memang selalu mengalah untuk anaknya.
Bagas
kembali menggendong tas gunungnya, melepaskan elusan tangan ibunya, hendak
pergi meninggalkan rumah. Sepersekian detik kemudian, guntur semakin
menggelegar. Jutaan butiran hujan semakin menghentak-hentakkan barang-barang di
bumi. Angin menggiringnya sehingga membuat tetesan hujan itu seolah-olah
berlarian. Tangan lembut ibu kembali merajut tangan anaknya. Kali ini lebih
kuat. Bagas menggeliat dan hampir membuat badan ibunya jatuh tersungkur.
Beruntung, geledeg yang mengamuk dan kilat yang menyambar menghentikan
langkahnya.
“Nak, dengarkan Emak!”
Sang ibu menuntun anaknya terduduk di kursi.
“Kamu
istirahat dulu. Di luar sana masih hujan lebat.”
Bagas
tak bisa berupaya apa-apa. Keadaan menyetujui kehendak ibunya. Alam mengetahui
bahwa sang ibu butuh pelukan anaknya. Bagas mengiyakan tanpa berkata-kata dan
kembali ke kamar. Sang ibu mengusap dadanya. Beberapa menit kemudian, ia
memandang foto usang suaminya yang terpasang di dinding.
Hujan
yang lebat membuat senja semakin gelap. Ia menutup gorden jendela dan mengunci
pintu rumahnya kemudian pergi ke kamar mandi dan mengambil air wudu.
Dikenakannya mukena putih mas kawin dari suaminya dan melantunkan ayat suci di dalam
kamar. Di kamar lain, Bagas menelungkupkan badannya dengan bantal yang menutupi
telinganya. Suara dering HP yang berbunyi berkali-kali dibiarkannya. Ia kesal.
Suara
lirih ibunya mengaji masih mengudara di kamar Bagas sampai ia ketiduran dengan
pakaian rapi yang belum sempat digantinya.
“Emak
mau ke mana?”
Senyum
ibu hemat sekali. Ia tak rela bahagia di atas penderitaan anaknya. Namun apa
daya, rasa itu tak mampu membuatnya bisa saling bertemu.
“Ibu
dipanggil Majikan, Nak.”
Muka
Bagas panik sepanik-paniknya.
“Lha,
Bagas sama siapa, Mak?”
Sang ibu
yang berbusana putih mengkilap semakin mundur menuju arah cahaya di
belakangnya. Suara lantunan ayat suci memanggil-manggilnya dari arah belakang.
Ia berusaha menarik tangan anaknya yang mengulur-ngulur mengharap bantuannya.
“Istriku,”
Ibu
menoleh ke arah panggilan. Suaminya memanggil dari arah cahaya itu.
“Siapa,
Mak?”
“Itu
ayahmu, Nak, ayahmu.”
“Mana?”
Bagas
tak dapat memandang ayahnya yang berdiri tak jauh dari ibunya.
“Bagas,”
Bagas
mengenali suara tegas itu. Ia adalah ayahnya. Ia menoleh-noleh mencari sumber
suara namun suara itu tak berwujud padahal telah menggamit tangan emaknya.
“Maafkan
emak, Nak. Emak harus pergi.”
“Bapa
juga, Nak.”
Sesosok
embun di pagi hari itu kian menjauh di pandangan Bagas yang terus mengulur tangannya.
“Ibu..........”
Bagas
terbangun menggeliat dari tidurnya dan mengedarkan pandangannya. Mukanya
berkeringat setelah mimpi yang merasuki alam bawah sadarnya. Ia baru tersadar
bahwa ia bangun pada sepertiga malam. Seketika itu ia berlari menuju kamar
ibunya. Ia menyibak gorden pintu dan ditemukannya sang ibu yang sedang tersujud
dalam shalatnya. Perlahan ia memasuki kamar ibunya. Lama ia menunggu ibunya
bangun dari sujud. Bagas terduduk sila di belakang ibunya. Putaran jam dinding
yang didengarnya memuai bagai sehari penuh. Ia tetap menunggu muka ibunya untuk
dicium dan dipeluknya. Pandangannya tertunduk mengumpulkan segudang asa untuk
pintu maaf ibunya. Lama sekali ia menunggu. Ia mengira bahwa ibunya lupa bacaan
atau rakaat shalat sehingga tak kunjung bangun dari sujudnya. Tangannya hendak
memegang pundak sang ibu untuk mengingatkan. Namun ia urungkan dan kembali
menunggunya dalam beberapa menit. Kamar itu hening. Hanya lolongan malam yang
di antara ia dan ibunya. Bagas semakin penasaran. Akhirnya ia pegang pundak
ibu. Ada perasaan aneh tatkala memegangnya. Bulu kuduknya berdiri. Bilik
rasanya mulai pecah ketika ia tahu bahwa sang ibu sudah tidak bernapas. Di
malam itu ia peluk ibunya kuat-kuat dan mencium mukanya yang sudah hilang
senyum tulusnya seraya berseru panjang.
“Ibuuuuuuuuuuuuuuuuu...................”

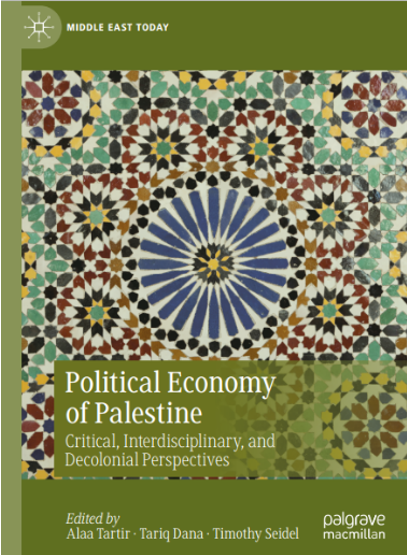


Comments
Post a Comment