{BUKAN} Pahlawan Kesiangan
Seorang bapak
tua bertopi hitam mengedarkan pandangannya ke sekeliling pemberhentian bus dan
angkot. Tatapannya lekat pada setiap pintu, berharap penumpang mengarah ke
sebuah becak yang terparkir di pangkalan. Berkali-kali ia mengibaskan topinya dan
mengelap keringat di dahinya dengan handuk kecil. Terik mentari menyorotinya
hingga dahaga mudah sekali ia rasakan. Roda becak hari ini tidak mengayuh
lancar, sepi penumpang. Hanya beberapa orang berumur tua yang menggunakan jasa
kendaraan ramah lingkungan ini.
Tak lama seorang
ibu dengan sejinjing keranjang belanjaan menghampirinya. Tono langsung memutar
haluan menuju arah yang dituju.
Di toko depan
sekolah menengah atas, ibu itu meminta becak berhenti dan membayar sejumlah
uang yang tak dilihat nominalnya oleh Tono. Hanya senyum yang terbalaskan untuk
setiap penumpang. Di saat yang bersamaan, anak-anak SMA sudah bubar dari
sekolah. Tono melihat Rantri, anaknya yang masih kelas sebelas tengah berjalan di
trotoar. Rantri menangkap tatapan ayahnya dan seketika melihat sekelilingnya
memastikan tiada mata yang mendapatinya pulang naik becak. Wajahnya mendung, sama
sekali tak memerlihatkan wajah berseri di depan ayahnya. Tono tak
mempermasalahkan muka yang tak terlukis senyum itu dan menyudutkan becaknya
tepat di depan sang nona cantik seraya mengulurkan tangannya hendak menyalaminya.
Rantri acuh dengan uluran tangan itu dan langsung duduk di jok becak memalingkan
mukanya dari bangunan sekolah seraya berkata : “Cepat, cepat, Pak.”. Uluran
tangan ayah langsung terhempas lemas dan segera mengiyakan titah sang nona
cantik yang terduduk di becaknya.
“Sudah
pulang, Nak?”
Pertanyaan
itu sepi dari jawaban.
“Nak?”
“Mmm.... “
Muka Rantri
masih kusut dan menjawab pertanyaan ayahnya dengan deheman. Tampaknya
sekumpulan teman-teman sekolahnya mendapatinya pulang sekolah naik becak. Di
antara lalu lalang motor teman-temannya, Rantri menyembunyikan muka cantiknya
dengan tas dan kerudungnya.
“Kenapa, Nak?”
Seketika Rantri
menghentakkan kakinya ke badan becak. Bruukk.
“Aduuh..”
Rantri menghentakkan
kaki pada tempat yang salah. Di ujung pijakan, Rantri menghujamkan kakinya
hingga hilang kendali. Ia terjorok ke depan hampir mencium jalanan.
Tono cemas
bukan main. Ia turun dari jok, menyelamatkan putrinya yang terjatuh. Rantri semakin
kesal. Ia memungut tasnya yang terlontar di depan badannya, bergegas berdiri
dan berjalan menjauhi ayahnya.
“Nak, mau ke
mana?”
Rantri berjalan
lunglai menuju gubuknya yang tak jauh dari tempat itu. Sang ayah
menggeleng-geleng kepala atas tindakan anaknya yang penuh pertanyaan. Ia tak
mengayuh becaknya melainkan mendorongnya membuntuti putrinya.
Sesampainya
di rumah, ia menggebrukkan badannya di atas kasur sambil membuka smartphone-nya.
“Ayah
malu-maluin Rantri saja.”
“Malu-maluin
gimana?”
“Rantri itu
pengen motor, bukan becak butut itu.”
“Sabar, Nak.
Besok ayah belikan.”
“Besok,
besok. Besok kapan?”
“Do’akan saja
ayah rezekinya lancar.”
“Do’a terus.
Apa gunanya do’a? Toh bapak yang sering shalat pun gak dikabulkan
do’anya.”
“Astagfirullah,
Nak. Istigfar, jangan bilang begitu.”
“Mulai besok Rantri
gak bakal pakai kerudung lagi, percuma taat tapi rizkinya gak telat.”
“Jangan,
Nak.”
Rantri mencopot
kerudung putihnya dan menjauh menuju kamarnya. Tono mengelus-ngelus dadanya.
---0---
Di suatu pagi
yang cerah, Tono membersihkan becaknya. Rantri sudah siap berangkat sekolah
dengan rambut pangjang sepundak yang dibiarkan terurai.
“Nak, ayo
berangkat.”
Rantri melengos
tanpa jawaban atau salam sekalipun. Sang ayah kehabisan pikir untuk
mengembalikan senyum anaknya yang hilang.
Tono kembali
melajukan becaknya. Sebuah dealer motor menjadi tujuannya. Ia membawa sejumlah
uang yang didapatnya setelah membobol celengan haji. Uang itu tak mencukupi
untuk membeli sebuah motor. HP butut dan sebuah cincin almarhumah istrinya
harus rela ia jual. Sebuah motor bebek bekas itu siap diantarkan ke alamat
gubuknya.
Matahari berada
tepat di atas kepalanya. Ia meliburkan diri dari mengojek becak dan langsung
menuju gubuknya. Ia tersenyum-senyum tak sabar melihat anaknya yang sebentar
lagi akan menaiki motor impiannya. Namun, bruukk. Sebuah mobil dengan
kecepatan tinggi menghantamnya dari arah satu meter. Walau Tono masih fokus dalam
kendalinya, ia tak mampu mengalahkan laju mobil yang sangat kencang. Hanya bagian
roda depan yang tersenggol namun badan Tono terlempar sejauh lima kilo meter
menyisakan luka di bagian kepalanya. Jalanan di pusat kota seketika ramai
sementara mobil itu melengos tanpa jejak. Jasad Tono dikerumuni sekumpulan
warga.
Seorang
relawan anak SMA berbaju PMR mengangkat jasadnya menuju trotoar. Rantri penasaran
dan ikut melihatnya. Ia menyibak sekerumupan orang. Naas, seorang korban yang
tewas itu ternyata adalah bapaknya sendiri. Rantri histeris dan menutup
mulutnya. Sebuah mobil ambulan membawa jasad ayahnya menuju rumah terakhir.
Rantri tak
sempat berganti pakaian. Ia menangis tersedu-sedu mengantar ayahnya yang
dipanggil Sang Ilahi. Pada tanah, ia menahan amarah sebab telah menguruk
ayahnya bersama cacing dan unsur-unsur hara, membuatnya semakin subur dan
membiarkan belatung menikmati dagingnya. Tak ada suara, tapi mulut Rantri
menganga, teriakan paling keras tanpa volume. Ia merasa ada setitik yang
menetes dari kedua ujung matanya. Lepaslah air bah, mendung akan segera
mengurung.
Ia pulang
sengkoyongan menuju gubuknya. Sepi, tak ada lagi suara bising ayahnya yang
menyuruhnya untuk shalat dan mengaji. Namun ia terheran dengan sebuah motor masih
berplastik yang terparkir di depannya. Segera ia merobek plastiknya. Becak
usang itu berubah menjadi sebuah motor. Rantri mendapati sebuah surat di atas
motornya lantas membacanya.
“Nak, selamat
ulang tahun, semoga panjang umur dan sehat selalu. Tak ada harapan dari ayah
untukmu selain kamu rela menjaga kerudungmu, menjaga akhlaqmu. Pakai terus
kerudungmu supaya kelak rambutmu tak menggantung di atas bara api neraka. Soal
rezeki sudah ada yang ngatur. Jadi taat pun harus tetap jalan. Semoga kamu
senang dengan hadiah dari ayah ini.”
Rantri terharu membaca surat itu. Ia sendiri
tak menyadari bahwa hari itu adalah hari ulang tahunnya. Kematian ayahnya
menjadi pelajaran berharga bagi hidupnya. Ia menjadi tahu bahwa ayahnya adalah
sosok pahlawan dalam hidupnya dimana ia selalu ingin memberi yang terbaik untuk
anaknya. Entah anaknya menyaksikan atau tidak, mengerti atau tidak, tapi hasrat
untuk berkorban itu selalu ada dalam darah dagingnya. Tubuhnya dinomor duakan.
Ketika anaknya berbuat sekeji apapun, tak ada benci bersarang di hatinya melainkan
do’a dan do’a.
“Mengapa baru
sekarang?”
Rantri
bertanya-tanya dalam hatinya, kecewa dan ingin marah pada waktu. Ia tak
sadarkan diri padahal setiap kali ia meminta, ayahnya selalu memenuhi. Hanya
soal waktu. Ketika Rantri meminta smartphone pada masa SMP, ayah
menangguhkannya. Bisa saja ayah membobol celengannya untuk membeli apa yang
Rantri minta. Namun ayah sayang Rantri sampai ia tak tega membelikan smartphone
walaupun kala itu sangat marak. Ibarat engkau meminta sesuatu kepada
Tuhanmu, mungkin saja Tuhan mengabulkan dalam waktu dekat, jauh, atau bahkan
tidak sama sekali. Bukannya Tuhan tak mendengar suara lirihmu berdo’a,
melainkan Dia tahu apa yang terbaik untukmu. Manusia memang serba tahu, padahal
Tuhannya lebih tahu. So ngatur, so mendikte Tuhan, protes kepada Tuhan, lalu
pergi meninggalkan aturan, mengira bahwa Tuhan lalai. Padahal betapapun seluruh
mahluk di muka bumi ini taat, tidak akan menambah kekuasaan-Nya. Begitupun
sebaliknya. Sungguhpun berbuat maksiat, tak akan mengurangi kekuasaan Tuhan di
muka bumi ini. Hanya manusia berjiwa ikhlas dan tawakkal yang boleh menerima
ketetapan Tuhan dengan lapang, baik dan buruknya.
Baru satu tahun masuk SMA, Rantri sudah minta
motor, mengancam ayahnya untuk melepas kerudung. Gejolak anak remaja dengan
emosi yang menggebu membuat hati ayah kalah. Ia merasa gagal menjadi ayah
karena Rantri memang selalu ingin menang, ayah mengalah. Hanya demi senyum
anaknya, ayahpun membobol celengan hingga akhirnya kematian menjemput. Rantri
terketuk hatinya oleh sebuah kematian. Kematian membuatnya kembali mengenakan
kerudung, mendirikan shalatnya.
“Ayahku bukan
pahlawan kesiangan.” Pekiknya dalam diam.
---0---

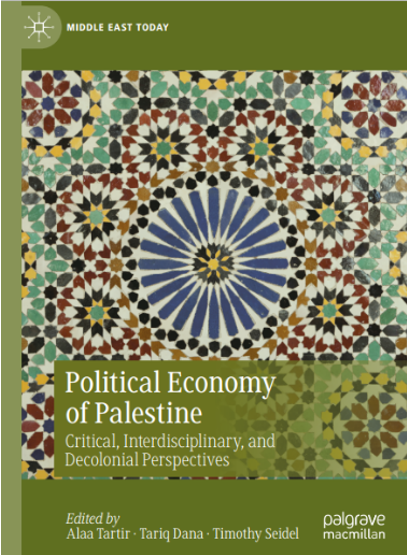


Comments
Post a Comment