Gundah Ala Santri
Butiran air hujan membasahi bumi pesantren An-Najah meninggalkan
suasana syahdu di sore hari. Senandung nadhom asmaul husna bersahutan dengan
rintik hujan. Kadang mengundang rasa kantuk ketika mengaji, serasa dininabobokan
oleh nyanyian hujan. Maklum, setelah membawa penat selepas belajar di madrasah
aliyah, mereka harus berbegegas ke aula menyandang kitab Mukhtarul Ahaadits
An-nabawiyah karya Sayyid Ahmad Al-Hasyimi. Kitab ini berisi hadits-hadits
yang tersusun secara alfabetis dari huruf alif sampai ya. Hal ini memudahkan
para santri untuk mengahafalkan haditsnya karena antara hadits satu dengan
hadits yang urutannya berdekatan cenderung bertema serupa. Kiai Didin tampak
selalu siap dengan wajah tulusnya menyemai untaian demi untaian hikmah hadits
Nabi. Santri terlarut dalam untaian cakrawala ilmu langit.
Di pojok satir[1]
itu, seorang santri berhijab lebar warna ungu tak hentinya menitihkan tinta di
atas buku catatannya. Buku itu ia taruh bersandingan dengan kitab Mukhtarul
Ahaadits. Ia tertunduk, jemarinya lihai menari di atas kertas, sementara
ceramah Kiai Didin mengudara menuju telinga, menepi di lubuk hati seorang
santri.
Zahira. Ia biasa dipanggil Zahira, si gadis berkulit putih
proporsional khas Melayu dan bermata bulat hampir sempurna. Ia dikenal banyak
santri di asrama putri karena dia seorang roisah[2]
asrama Rabiah Adawiyah.
Bukanlah Kiai Didin jika tidak ada guyonan dalam ceramahnya.
Sepasang telinga yang mendengar jeli dawuhannya akan tertawa serasa ada yang menggelitikan
pinggang. Para santri kembali terbangkit dari anggukan kantuknya yang tak
tertahankan.
Kajian berakhir.
Setiap hari Zahira menuju ke kantor untuk menunaikan amanahnya. Jika
tidak mengambil obat-obatan, ia mengisi tinta spidol, atau hanya sekedar
mengecek kantor. Ia berlalu lalang antara kantor dan asrama memantau keadaan para
santri tiap kamar. Jika ia menjumpai santri yang sakit, maka segera ia tangani
lalu ia beri obat atau dirawat di klinik pesantren jika diperlukan penganganan lebih
lanjut. Kadang ia juga menjumpai santriwati nakal yang meloncati pagar asrama,
pulang malam tanpa seizin pengurus. Suatu malam, ia menjumpai santriwati nakal yang
tertangkap basah di depan ibu roisah. Zahira yang mengenali muka itu lantas
mencatatnya. Sudah tidak salah lagi bahwa ia melanggar peraturan pondok.
“Lain kali izin pengurus terlebih dahulu jika ada acara luar pondok
supaya gerbang utama pondok terbuka untukmu. Teteh kasihan lihat kamu harus
loncat pagar segala. Janji ya Birul, Tina ?” ujarnya dengan tegas.
“Iya Teh, kami janji.”
Birul dan Tina lantas menyalaminya dan terberingsut pergi menuju
kamar.
“Gimana perkembangannya asrama bulan ini Zahira?” Tanya ustadz
Rahmadi, ketua umum santri putra dan putri.
“Alhamdulillah Ustadz, sejauh ini terpantau kondusif. Ada
beberapa santri yang sakit ringan dan telah kami tangani. Kebanyakan sakit
demam. Mungkin karena cuaca dingin dan sebagian santri kurang daya tahan
tubuh.”
“Bagaimana untuk yang
lainnya?” Ustadz Rahmadi menyebarkan pandangan kepada segenap pengurus santri
putri.
“Dua orang santriwati ketahuan loncat pagar pondok. Tiga hari yang
lalu tepatnya. Keduanya telah kami sidang di kamar pengurus dan terbukti
melanggar peraturan pondok, yaitu keluar malam lewat pukul 20.00 tanpa seizin
pengurus.”
Ustadz Rahmadi hanya mengangguk.
“Bagaimana dengan santri putra, Aiman ?”
Santri berkumis tipis dengan jenggot berusia muda itu adalah rois[3] asrama
Abu Bakar. Dengan lantang dan suara tegasnya ia angkat bicara. Ia tetap dalam
ketawadhuannya, tampak dalam suaranya yang direndahkan di depan ustadz-nya.
“Alhamdulilah sampai saat ini terpantau aman dan lancar.
Pembayaran uang SPP bulanan pun juga mengalir,” ucapnya.
“Namun ada permasalahan klasik tadz. Sebagian santri mengeluhkan
sandal dan sepatu yang dighasab[4]
terus-menerus. Bahkan ada yang hampir tidak kembali lagi,” tambahnya. Aiman
sedikit melukis senyumnya. Disambut barisan pengurus putri di seberang meja
berbentuk segi empat. Tidak kurang dari lima orang di setiap pengurus putra dan
putri.
“Iya, Aiman, Zahira. Saya rasa itu memang permasalahan klasik di
berbagai pesantren. Dari kaca mata negatif, itu memang sebuah pelanggaran
secara syariat muamalah. Namun jika kita melihat dari sisi lain, budaya ghasab
juga mencerminkan kekeluargaan di antara para santri. Betul tidak ?”
Ustadz Rahmadi memulai tawa ringan, disusul para pengurus. Seisi
kantor tertawa renyah.
“Itu hanya alasan bagi santri peng-ghosob. Mereka berdalih
bahwa semua barang yang ada di pondok itu milik semua santri. Pohon mangga
depan rumah kiai pun milik santri. Katanya sih semua barang pondok itu
milik santri. Tapi anehnya, tidak semua barang santri itu milik pondok.”
Tawanya masih berkelanjutan. Setelah reda, Aiman kembali angkat
bicara dengan mengacungkan tangan terlebih dahulu.
“Tapi Ustadz, saya punya inisiatif lain untuk meminimalisir kasus ghosob
yang sudah merajalela ini.”
Ustadz Rahmadi meliriknya, tampak mempersilakannya untuk angkat
bicara.
“Terlintas di pikiran saya untuk membuat sebuah regulasi baru. Jadi
setiap santri wajib menaruh sandal sepatunya di rak sepatu yang ada di dalam
kamar. Jika dibiarkan di depan kamar atau di tempat yang sekiranya itu tidak
pantas dipandang sebagai tempat ditaruhnya sepatu, maka dibuat sebuah
kesepakatn bersama bahwa barang itu halal untuk dighasab. Saya harap
regulasi baru ini bisa meminimalisir keluhan santri yang kehilangan sendalnya.”
“Bagaimana langkah mensosialisasikannya?”, kritis Ustadz Rahmadi.
“Lewat maklumat berupa kertas yang ditempel di papan pengumuman
serta maklumat langsung secara lisan ketika musyawarah bulanan seluruh santri.”
“Ide bagus dan bisa diterapkan. Bagaimana jika hal ini diterapkan
di asrama putri juga, Zahira?”
“Saya rasa tidak perlu ustadz. Karena kasus ghosob-mengghosob di
asrama putri tidak terlalu sering. Namun jika dimaklumatkan di asrama putri
juga akan lebih baik Ustadz.”
Kalau begitu, maklumatkan
saja kepada seluruh santri. Semoga membawa kemajuan untuk pesantren kita ke
depannya. Aamiin...”
Rapat mingguan pengurus santri putra dan putri itu berlangsung
khidmat.
---0---
“Zahira, ini surat maklumatnya sudah bisa dibahas pada musyawarah
santri. Coba dicek terlebih dahulu.”
Aiman menyerahkan seberkas kertas kepada Zahira di depan kantor. Zahra
menerimanya. Setelah beberapa saat, Aiman lantas berbalik badan kembali ke
asrama.
“Tunggu! Suratnya belum distempel.”
“O iya, aku lupa. Aku ambilkan dulu ke kantor putra. Intadhir
huna![5]”
Nia, teman Zahira membisikinya untuk cepat-cepat beranjak dari
kantor.
Setelah beberapa saat, Aiman datang membawa stempel, membubuhkannya
di kertas, lalu beranjak dari kantor.
Di sela kesibukannya belajar di sekolah dan mengaji di pesantren,
para pengurus santri ini meluangakan banyak waktunya untuk kepentingan
pesantren. Satu sama lain saling bahu-membahu menciptakan suasana pesantren
yang sesuai dengan cita-cita pesantren. Mulai dari lingkungan pendidikan,
kesehatan, keamanan, dan ketertiban. Di sela waktu formalnya untuk rapat,
adakalanya pengurus mengagendakan acara santai seperti ngaliwet[6].
Kedekatan antara pengurus pun semakin erat, dan memicu semangat kinerja
mereka.
---0---
Kamu tahu, di antara sekian banyak pertemuan, akan ada sekelebat
rasa yang mampir di hati ? Manusiawi ? Lelaki siapa yang tidak merindukan
kejelitaan Zahira yang pintar dan aktif ? Tak terkecuali Aiman. Bayangan wanita
itu selalu tersangkut di pelupuk matanya.
“Gimana, ketemuan sama bu roisahnya, seneng kan?” Tanya Darsim.
“Wis, apaan sih? Buat kepentingan rapat kok seneng.”
“Kali aja. Tuh, kan senyu-senyum sendiri.”
“Kamu tahu kabar bahwa Zahira akan menikah seusai lulus nanti?”
Sahut Bani.
Aiman menggeleng, mengisyaratkan Darsim untuk melanjutkan
ceritanya. Di perjalanan menuju asrama, mereka bertiga memperbincangkan sesuatu
yang menarik penasaran Aiman.
“Seperti biasanya lah Man. Perempuan cantik, pintar, dan putri
kiai, pasti sudah banyak yang antre. Dan kamu sepertinya telat Man.”
“Telat apanya Ban?”
“Telat untuk mengkhitbah[7]
Zahira.”
“Ah, kamu ada-ada saja.”
“Tapi kamu nyesel kan?”
Aiman terbatuk. Di bawah pohon taman asrama ini, ia edarkan
pandangannya. Mereka terhenti sejenak dan duduk di taman depan asrama.
“Memang belum saatnya bagiku untuk meminang perempuan. Apalah daya
aku, hanya seorang santri....”
“Dengan segudang prestasi dan pengalaman berorganisasi, tampan, dan
dekat dengan kiai pula.” Potong Darsim. Aiman menggeleng.
“Entahlah apa yang kamu bicarakan. Yang penting aku sediri tidak
menyesal. Toh pada saatnya, nanti akan tiba jodoh kita. Sekarang itu
masa-masanya memperbaiki diri. Orang baik tetep untuk orang baik kan dalam
Al-Qur’an nya?”
“Siap ustadz. Betul.”
“Nah, kamu tahu sendiri kan.”
“Tapi Man, perempuan harus kita cari juga kali..” protes Darsim.
“Iya. Kan pada saatnya Dar.”
“Saatnya kapan? Kalau dinanti-nantikan, takutnya sudah direbut
orang.”
“Ya enggak lah Dar. Maksudnya, saatnya itu ketika kita sudah
mapan dan siap untuk berkeluarga. Sudah toh, yakinkan saja pada Dzat
yang telah menciptakan makhluqnya berpasang-pasangan.”
“Beneran nih, gak mau ancang-ancang buat nyari jodoh? Nanti keburu
direbut orang loh...” rayu Bani dengan sekilas tawa.
Perkataan itu sedikit menggelitik Aiman. Ia beristigfar dalam
hatinya.
“Astagfirullah,, ini memang ujian para pemuda Ban, dari
zaman dulu hingga kini. Pemuda itu masanya merasakan kematangan hasrat
manusiawinya. Katakanlah pacaran. Jika nafsu kita menurutinya, maka tamatlah
riwayatmu karena sudah dikelabuinya.”
“Apa nafsu perlu dimatikan? Kan lebih gak wajar Man.”
“Bukan. Nafsu dalam diri kita hanya akan mati ketika nyawa kita
sudah dicabut oleh Yang Kuasa. Artinya nafsu itu memang bagian dari diri kita.
Kita hanya perlu mengeremnya, bukan memusnahkan.”
“Lha gimana toh kamu ini Man, bingung aku. Katanya pacaran itu
manusiawi. Tapi katanya gak boleh karena itu nurutin hawa nafsu. Piye iki?”
Percakapan itu berlalu seiring senja yang semakin menua.
--0—
Di suatu sepertiga malan, Aiman terbangun seperti biasnya. Ia sudah
kebal dengan dinginnya air wudhu yang membasahi kulitnya. Beberapa santri juga
sudah terbangun mengisi shaf demi shaf masjid. Lampu tampak belum nyala. Santri
terhanyut dalam sujud tahajjudnya. Di shaf paling depan itu, Aiman menegakkan
takbir. Tampak lama sekali ia berdiri. Rupanya ia mengulang hafalan Qur’annya
ketika shalat. Kemudian ia ruku’ i’tidal, lantas sujud. Dalam sujudnya, ia
tampak lebih lama daripada rukun yang lainnya. Ia kerahkan semua rintihan do’a
dan harapannya dalam keheningan sepertiga malam. Hanya Tuhan dan ia seorang
diri yang tahu cita-citanya. Seperti inilah gundah ala santri.
[1] Sebuah kain penghalang antara
santri putra dengan santri putri. Biasanya berbentuk gorden yang bisa dibuka
tirainya sewaktu pengajian berakhir.
[2] Ketua putri
[3] Ketua putra
[4] Dipakai orang
lain tanpa sepengetahuan dan tanpa seizinnya.
[5] Tunggu di sini
[6] Berkumpul dan
makan bersama di atas daun pisang dengan menu nasi liwet khas Sunda. Biasanya
cukup dengan lauk ikan asin peda dan sambel.

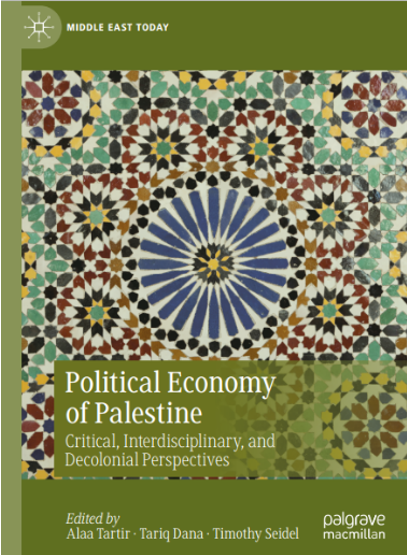


Comments
Post a Comment