Berhati makkah
“Kamu serius mau kuliah ke Jerman?”
“Serius.”
“Gimana dengan
iman yang terpatri di hatimu? Masih bersikeras mau ke Jerman? Mau dibawa ke
mana almamater pondokmu?”
Ia menundukan kepala.
Zaki menarik
nafas. Debur air sungai Nil riuh ditiup angin yang cukup kencang. Di tengah
sibuknya Kota Kairo, Zaki dan Rendi terduduk di maqha[1]
yang menghadap ke muka sungai terpanjang di dunia itu.
“Insya Allah saya
siap, Ren.” jawabnya tenang.
Rendi kecewa.
Bukan jawaban itu yang diharapkan.
“Tapi kan sayang gelar
Lc yang nyantol di namamu. Sekian tahun kamu menimba ilmu agama dan kamu buang
begitu saja dengan mengambil magister jurusan lain.” Protes Rendi. Ia
menyeruput ‘ashir[2]
segarnya.
“Lulusan agama gak
boleh terjun ke dunia umum? Gak boleh jadi dokter, polisi ataupun pengusaha?”
Rendi tertegun.
Diamnya adalah jawaban dari pertanyaan yang dilontarkan Zaki.
“Terus siapa yang
menduduki kursi itu? Non-muslim?” Zaki meneruput kembali ‘asirnya. “Islam
bukan agama sekuler. Dunia terangkul oleh Islam. Nabi Muhammad dalam
kesehariannya tak lepas dari hal-hal keduniaan. Apalagi beliau di samping
seorang kepala agama adalah seorang kepala negara. Dunia dan akhirat adalah
sama di mata seorang muslim. Namun dalam kadarnya memang akhirat lebih
diutamakan. Dengan pendalaman kita akan ilmu akhirat itulah yang menjadikan
niatku untuk melanjutkan kuliah S2 ke Jerman tak goyah.”
Matanya menikmati deburan nil yang damai.
“Sempat terlintas dalam pikiranku dengan apa yang kau katakan. Aku
ceritakan kabar beasiswa yang kuraih ini kepada orang tuaku. Bercak kesedihan
terlukis di wajah mereka. Tapi itu tak lebih dari sekedar khawatir mereka
kepadaku. Akhirnya mereka mengizinkanku.” Jelas Zaki.
“Syukurlah kalau begitu.
Semoga sukses. Ke manapun kamu kuliah, persahabatan kita jangan terputus. Aku
akan meneruskan S2 di ma’had aly pondok Al-falah sekaligus mengabdi di sana.”
“Iya sobat.
Sampaikan salam saya kepada teman-teman. Salam dari Zaki Mubarak.”
“Insya Allah.”
“Oh iya sobat.
Kalau nikah, jangan lupa undang aku ke walimahnya. Syukur-syukur pas aku pulang
ke Indonesia.”
“Pasti.”
Di penghujuang
kuliahnya, Rendi dan Zaki mengisi libur pasca wisuda di sungai Nil. Mereka
adalah santri terbaik di pondoknya dan mendapat beasiswa kuliah di Al-azhar,
Kairo.
---0---
Pesawat Garuda
mendarat di belahan bumi Eropa, tepatnya di Bandara Zurich. Bandara ini tak
sebesar bandara Eropa pada umumnya. Namun ia terkagum dengan bar kotaknya yang
dibangun memanjang sepanjang elevator utama. Bar berbentuk seperti potongan
cokelat itu diletakkan di sudut bandara. Lampu terang benderang menyala dari
dalam bar. Terkesan ekslusif dan ellegant.
“Munich University”. Zaki bekumpul dengan mahasiswa-mahasiswa dari berbagai
penjuru dunia. Gabriel dan Kamil adalah dua teman barunya yang ia kenal di KBRI
Jerman. Mereka sama-sama dari Indonesia dan mengenyam jurusan yang sama, kedokteran.
Mereka bergabung dalam oganisasi PPMI Jerman dan tinggal di sebuah apartemen.
“Perkenalkan nama saya
Zaki dari Sukabumi.” Ucapnya sambil menjulurkan tangan dan menyalaminya.
“Gabriel, dari
Surabaya.”
Ia membungkukkan
sedikit badannya hingga terlihat kalung salib di lehernya.
“Saya Kamil dari
Garut.”
Sudah tertebak
dari logat uniknya yang berbau Sunda.
“Kuliah semester
berapa mas?” tanya Zaki.
“Tiga.”
“Bagaimana
pengalamannya kuliah di Jerman?”
“Kamu akan
menemukan hal-hal unik yang harus kita input ketika pulang ke Indonesia.
Soal pendidikan jangan kau tanya lagi. Apalagi kedokteran.” Jawab Kamil.
“Ujian
semesternya?”
“Itu sih relatif.
Contohnya teman saya ini, Kamil. Dia BJ Habibinya masa kini.” Ucap Gabriel
menepuk pundak Kamil.
“Ah, kamu bisa saja.
Tapi betul juga apa kata Gabriel. Kalau kamu berjuang keras hasilnya akan
mengagumkan dan jadi orang TOP di sini. Cari kerja, gampang. Tapi
sebaik-baiknya kamu di sini, contohlah Pak Habibi. Ia menuai kesuksesannya
bukan di negara lain, tapi negara sendiri. Walaupun minim apresiasi layak dari
pemerintah, tapi hatinya untuk Indonesia.”
“Ngomong-ngomong,
kamu lulusan mana?” Celoteh Gabriel.
“Universitas
Al-azhar, Kairo ngambil Syariah.”
Kamil lantas
memeluknya.
“Masya Allah,
khirrij sanah kam?” [3]
“Hadzihissanah.”[4]
Mereka tampak akrab. Sebenarnya Zaki hendak menanyakan kondisi Islam
di Jerman. Namun ia urungkan.
Salju menyambut bulan pertama di langit Jerman. Kamil meminjamkan
jaket tebal kepada Zaki.
Jarak kampus dari apatemen hanya lima menit ditempuh dengan taksi.
Tapi mereka lebih memilih jalan kaki bersama mahasiswa lainnya menikmati
pemandangan kota yang tertata rapi dan bersih. Memang pejalan kaki di tanah
Eropa lebih banyak daripada pengendara mobil.
Zaki mulai beradaptasi.
“Kalau Jerman ditapaki oleh mahasiswa soleh seperti kamu, jadi berkah.”
bisik Karim.
“Berkah gimana?”
“Mahasiswi-mahasiswi berbusana tertutup. Mereka pakai jaket tebal
dan topi khusus.”
“Apa hubungannya dengan kehadiran saya? Kalau musim saljunya sirna,
mereka akan jual kembali aurat-auratnya.”
“Hahaha... Betul juga Zak.”
Zaki menggigil. Kulitnya masih sensitif dengan cuaca baru.
Karim mempekenalkan kampus barunya.
“Itu dosen kita.”
Karim menunjuk seorang pemuda berkulit putih, rambut pirang, dan berjas
hitam yang terduduk di meja bawah pohon bersama sekelompok mahasiswa yang
sedang berdiskusi.
“Semuda itu ia jadi dosen?”
“Ya. Dosen muda banyak di Jerman. Dosen yang 10-20 tahun lebih muda
dari dosennya sudah biasa. Telebih ketika mengajar mahasiswa asing seperti
kita.”
“Kok bisa ya?”
“Kita lihat satu sample. Bedakan cara jalan mereka dengan
kita”
Zaki mengamati orang-orang yang berlalu lalang di sekelilingnya.
“Dari jalannya saja sudah terlihat bagaimana kinerja kesehariannya,
cepat, tanggap, tidak bertele-tele. Jarang bahkan hampir tidak pernah ada undangan
yang datangnya telat. Orang macam kita, santai saja. Ada undangan jam 8,
datangnya jam 9. Hahaha.....”
“Beliau meraih post doctoralnya di usia 21 tahun. Orangnya jenius.”
Tambahnya.
“Siapa namanya?”
“Professor Zach. Beliau mengajar kita setiap Hari Rabu.”
Mereka menuju ruang belajar.
---0---
Salju mematikan rasa pada tubuh Zaki. Malam itu ia terbangun
kemudian menyibak gorden jendela. Butiran salju hingap di kaca. Kota terlihat
indah dari lantai 7 apartemen. Ia hendak mengambil air wudhu lalu keluar kamar
menuju ruang sempit di belakang apartemen bersebelahan dengan dapur. Di sana
mereka shalat tahajjud. Dua sajadah kecil terhampar di ruangan berukuran 2 x 3
meter.
Seusai tahajjud, mereka menuju taman menghadap kota yang berselimut
salju tebal.
“Mas, gimana kondisi muslim di Jerman?”
Karim menarik nafas.
“Islam tanpa muslim, muslim tanpa Islam.”
“Maksudnya?”
“Kita lihat orang Islam yang hidup di negara minoriras muslim.
Mereka sangat taat beragama. Salah satu contohnya, muslimah ingin sekali berhijab
dan kesusahan mencari pekerjaan yang membolehkannya berhijab. Akhirnya sebagian
mereka memakai wig sehingga terlihat tak berhijab. Itu cerita dulu. Sekarang, populasi
Islam di benua Eropa sudah meningkat walaupun beberapa daerah memang masih
melarang wanita berhijab. Sementara di negara mayoritas Islam kita temukan banyak
muslim yang memeluk Islam secara setengah-setengah, tidak kaffah[5].
Islam yang sekedar KTP dan menjadi bunglon di antara jutaan muslim di
sekitarnya. Kita sulit membedakan mana wanita muslimah atau tidak karena
sama-sama tak berhijab.”
“Banyak?”
“Tak banyak, namun ada. Itu yang menjadi PR kita yang ditugaskan
oleh kiai.”
“Mas, kalau boleh tahu, kenapa Mas tidak melanjutkan S2 di Timur
Tengah saja?”
Zaki menanyakan pertanyaan yang dilontarkan Rendi kepadanya.
Karim menuju kursi panjang.
“Kiai pernah berkata. Jadilah muslim yang berotak Jerman dan berhati
Makkah.”
Zaki mengangguk.
“Jerman sebagai barometer negara berdedikasi tinggi dan
penghasil teknologi maju. Makkah menjadi kiblat muslimin seluruh dunia dan
menjadi barometer sejarah Islam. Tak semua penduduk tanah suci itu baik dan Islami.
Namun dengan kehadiran Islam di jazirah Arab serta banyaknya nabi dan rasul
yang diutus untuk membumikan Islam, membuatnya bumi yang Islami sehingga
menjadikannya tempat yang mustajabah untuk berdo’a.” Kamil mengubah posisi
duduknya.
“Sementara dalam arti maknawi, kita harus menjadi muslim sepintar
orang Jerman dalam berdedikasi dan setaat orang Makkah memeluk Islam.”
Zaki semakin paham.
Mentari merangkak
naik. Langit Jerman melelehkan salju yang menyelimuti sudut kota. Musim salju
segera sirna. Zaki berangkat ke kampus.
Ia mengambil air
wudhu lalu ia memasuki ruang kuliah. Kehadiran mahasiswa lain yang tampaknya ahli
dalam bidang kedokteran sempat membuatnya minder. Namun ia tak menganggapnya
serius, sewajarnya saja. Sejarah prestasi bidang biologi yang diraihnya di MTs
dan MA akan diukirnya kembali menghasilkan relief-relief prestasi yang lebih
gemilang dan nyata. Ia yakin bisa menguasai mata kuliahnya. Semangat Ibnu Sina
berkobar di dadanya.
Seusai
pembelajaran di kampus, ia mengunjungi perpustaan kota. Kereta U-Bahn[6] mengantarkannya
ke gedung perpustakaan yang bertubuh klasik, megah, lengkap dan menyimpan nilai
sejarah.
Hatinya berdetak
keras. Mahasiswi-mahasiswi berpakaian minim duduk di sampingnya. Dua sejoli
berciuman. Jangankan dua sejoli, sejenispun ada. Pemandangan yang menggoyahkan
iman. Iman yang belum berpatri kuat dalam hati. Hati yang lengah terhadap
pengawasan Tuhan.
Ia menuju kamar
mandi untuk memperbarui wudhunya. Diambilnya sebuah buku tebal di rak lalu disantapnya.
Langit menjelang
sore. Pengunjung meninggalkan perpustakaan menyisakan mereka yang masih sibuk
melahap buku dan mengerjakan tugas kuliah. Mereka adalah para mahasiswa. Tak
terkecuali Zaki. Ia fokus melahap buku-buku tebal.
Dua tahun
kemudian
Zaki berada di penghujung masa kuliah magisternya. Seringkali ia
diminta menghadap Dosen guna mengikuti ujian lisan dan diskusi-diskusi
kesehatan.
Zaki menelusuri
lorong menuju ruangan dosen. Sepanjang perjalanan, ia mengagumi ornamen klasik
bangunan dengan hamparan karpet di sepanjang lorong dan sorotan lampu terang di
setiap bagian atas figura foto. Ia sampai di ruang nomor 16 bertuliskan Profesor
Carl, spesialis bedah. Diambilnya kartu ujian dan mencocokan kembali nama dosen
yang tertera di jadwal. Ia yakin ini adalah ruangannya. Lalu ia mengetuk pintu.
Setelah satu
ketukan pintu, seorang dosen muda berkulit putih dengan rambut panjang terurai,
bersepatu hak sedang muncul di balik daun pintu. Dialah Professor Carl. Zaki
tak kuasa memandang dosennya yang mengenakan kaos ketat dengan warna mirip
kulitnya dan berok pendek. Dosen menyambutnya dengan senyum manis. Mata Zaki
shock melihat pakaiannya yang minim dan ketat seperti ketupat, luar
memperlihatkan lekukan dalamnya. Nyaris tak berbusana.
“Wenn Ihr Professor Carl?[7]”
tanya Zaki.
“Willkommen.[8]”
Perempuan itu mengangguk, mempersilakannya masuk dan duduk di kursi depan
meja kerjanya. Zaki menundukan pandangannya. Sesekali ia melihat-lihat
buku-buku tebal tertata rapi di rak sudut ruangan. Dosen menyambutnya ramah dan
memperkenalkan dirinya. Katanya, ia terkagum dengan kedatangan seorang
mahasiswa dari Indonesia.
“Kamu kenal BJ Habibi?” tanyanya dalam bahasa Jerman. Dengan bangga
Zaki menjawab, “Ya. Beliau adalah presiden ke-tiga Indonesia.” Senyum simpul
terlukis di bibir dosen. “Aku kagum padanya. Sampaikan salam dari saya, Carl,
anaknya dosen yang dahulu mengajarnya.”
To the point,
sang dosen memberinya pertanyaan-petanyaan penting seputar kedokteran,
khususnya dokter bedah. Zaki menjawabnya dengan percaya diri. Acap kali dosen
itu mengangguk-ngangguk puas dengan jawabannya. Berkali-kali ia memujinya.
Sampai-sampai ia menyebut Zaki sebagai cucu Habibi. Sontak Zaki tersenyum
mendengar guyonan sang dosen. Meski demikian, rasa was-was masih dirasakan Zaki
yang membuat kepalanya enggan menengadah. Tapi ia puas dengan
pertanyaan-pertanyaan yang mengelitik wawasan keilmuannya.
Tak terasa sudah dua
jam ia duduk di kursi. Dosen mengakhiri
ujian lisannya dan mempersilakannya pulang.
Sempat terbesit rasa kecewa, putus asa dan menyerah di hatinya
untuk kembali menemui dosen yang nyaris telanjang itu. Zaki adalah laki-laki
normal. Pemandangan itu cukup memancing syahwatnya. Istigfar diucapkannya
setiap saat. Pandangan mata yang jatuh di aurat seorang wanita itu masih
membekas di pelupuk matanya dan dosa membayanginya.
Ilmu dan iman bagaikan sekeping logam yang sama pentingnya untuk
diraih. Alhasil, ia terus berusaha menerjang bisikan iblis yang senantiasa
membuat manusia terlena dan ia tak akan berhenti menggoda manusia. Janji itu disaksikan
Tuhan, Adam dan dirinya ketika hendak turun ke bumi untuk menggangu manusia,
menggoyahkan manusia dari jalannya.
Minibus mengantarkannya pulang ke apatemen. Ia melirik jam tangan.
Sudah pukul 11 malam. Sesampainya di apartemen, ia sempatkan untuk shalat witir.
Sebelum tidur, ia kembali melahap buku tebal dengan beberapa judul
kedokteran. Saking nikmatnya baca buku, ia sampai lupa waktu. Jarum jam sudah
menunjukan lewat dari tengah malam.
Dingin menusuk tulang dan syarafnya. Ia tutup jendela dan ventilasi
udara. Lalu ia mengambil wudu dan merebahkan badan. Wirid mengantarkannya ke
alam mimpi.
Keesokan harinya ia
kembali setor wajah di hadapan dosen. Pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan
lebih menantang dan memaksa Zaki untuk mengerahkan wawasan keilmuannya di hadapan
dosen. Sang dosen merasa puas dengan jawaban Zaki. Ia dianggap lulus dan layak
mendapatkan ijazah S2 dengan predikat Cumlaude.
Tibalah wisuda
mahasiswa magister dari seluruh fakultas di Munich University. Gedung megah dan
klasik dihadiri seluruh dosen. Satu per satu mahasiswa maju ke depan dan
mengenakan medali kelulusan.
Lega dirasakan
Zaki, Karim beserta mahasiswa lainnya. Ia berkemas di apartemennya untuk pulang
ke tanah air. Ia melirik laptop yang masih menyala di meja. Satu pesan masuk
dan lantas membukanya. Ada pesan dari bapak bupati.
Zaki,
bagaimana kabarmu di Jerman? Senang rasanya putra Sukabumi bisa terbang ke sana
untuk mencari ilmu. Bapak ucapkan selamat atas keberhasilanmu.
Ada
sebuah tawaran dari koran harian Islami. Sebuah rubrik bertemakan “hikmah”
dipersembahkan untukmu. Senang rasanya jika Zaki bisa menerimanya.
Tak hanya itu, kamu juga diminta
untuk mengisi seminar keislaman di berbagai pondok dan rumah sakit islam di
daerah Sukabumi. Terutama di pesantren almamatermu, Al-Falah. Kiai Arifin sudah
menantimu. Kamu diminta untuk menceritakan pengalamanmu mencari di ilmu di dua
negara dengan wajah berbeda, Mesir dan Jerman.
Sekian
pesan dari Pak Syamsu. Selamat datang di tanah air.
Terima kasih.
Mata Zaki
berbinar-binar bercampur bangga. Semenjak saat itu, Zaki menebar ilmunya untuk
masyarakat di daerahnya, menebar nilai-nilai keislaman, dan membumikan
nilai-nilai toleransi di muka bumi.
---0---

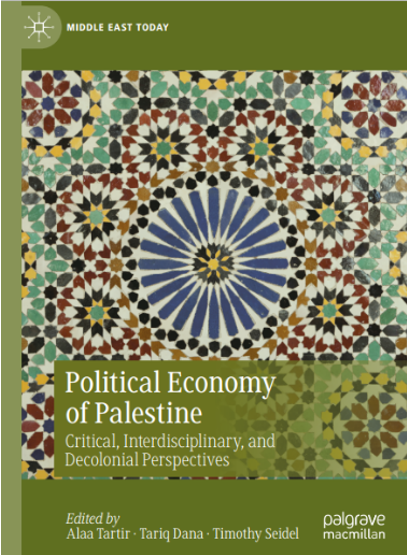


Awesome 🖒
ReplyDelete