Bahasa Rindu (sebuah cerpen karya Fadlan S)
Di serambi masjid lantai dua, Hari biasa memandang gugusan bintang,
menghabiskan waktu hanya untuk berkontemplasi. Ketika santri lain tertidur,
matanya terbuka memandangi wajah malam. Sabit berdiri gagah. Dingin memeluk
sepertiga malam. Sorban putihnya terkalung di lehernya untuk menepis dingin
yang menusuk kulitnya. Kopiah songkok menutupi rambunya. Tatapannya terpaut
pada satu bintang.
“Wahai Tuhan
pencipta bintang yang tak terkalahkan gemerlapnya, apakah pondok ini benar
mengantarkanku menuju jalan-Mu? Sudah sekian purnama aku menjadi anggota pondok
namun belum menenangkan rasaku.”
Hari
mengalihkan pandangannya menuju sabit yang gagah.
“Wahai Tuhan
pencipta gagahnya sabit, sampaikan salamku untuk ayah ibuku.”
Tetesan
sebening kristal menetes dari matanya.
Hari merasa
terpenjara dalam sebuah pondok yang tak dikehendakinya. Ayah dan ibunya seolah menelantarkan
Hari dalam kehidupan sengsara. Ia tak sebebas dulu di kampungnya. Peraturan
ketat membuatnya sulit bergerak. Iapun harus berkamuflase dan menjadi bunglon
di antara ribuan santri. Sorban terlilit di lehernya, bersarung dan berkopiah.
Namun ia belum menemukan titik terang perantauannya.
Ketika dahulu
ia bisa bebas main band, kini ia harus tertunduk pada sebuah Al-qur’an. Jika
lagu-lagu terbaru giat dihafalkannya, kini ayat demi ayat sucilah harus
dihafalnya. Perempuan pujaan hatinya harus terlepas dari kehidupannya.
Teman-teman di kampungnya kini berjauhan dengannya. Bukan berjauhan,
sebenarnya. Hari hanya berkelana sebatas waktu studi untuk mencari ilmu, memperluas
pergaulan, menambah guru dan pengalaman. Jauhnya ia dengan teman-temannya di kampung
hanya alasan-alasan saja, padahal sebenarnya setiap semesteran ia bisa bertemu.
Pondok
membuatnya terus berkontemplasi. Secara tidak langsung dan tidak dirasakan
Hari, pondok mengajarkannya untuk menjadi dewasa. Pekerjaan siapakah mencuci
pakaian? Pekerjaan sang istri bagi suami, pekerjaan ibu bagi sang anak,
pekerjaan kakak perepuan bagi sang adik. Namun seorang santri terbiasa mencuci
pakaiannya sendiri, menjemurnya dan melicinnya. Kalau dalam satu minggu saja
tidak mencuci, santri tak bisa menutupi auratnya kecuali tubuhnya gatal-gatal
mengenakan pakaian yang tak diganti-ganti.
Berbagai macam
kegiatan pondok menyibukkannya dan menjadikannya berpikir kritis untuk mengatur
waktu. Bermacam pelajaran harus ditekuni, minimal di atas rata-rata dan tidak
mengulang ujian. Acara pondok seperti kegiatan latihan berpidato, tadarrus,
kajian kitab ataupun masalah keorganisasian. Semuanya tak mungkin dilewatkan seorang
santri kecuali ia dihukum oleh bagian keamanan dan pendidikan. Satu dua kali Hari
masuk mahkamah (persidangan). Namun tak apa, hal itulah yang membuatnya
terkesan dari sebuah kehidupan di pondok. Rasanya kurang lengkap jika tidak
merasakan apesnya dihukum.
Kegiatan
belajar mengajar di sekolahpun sangat menyita waktunya. Seharian penuh ia harus
terduduk di kursi menyimak proses transfer ilmu dari guru. Bahkan sampai sore
menjelang. Dua tiga kali tertidur di sekolah tidak mengapa. Itu hanya sebagai
pelengkap bagi penyandang status santri untuk cerita di masa nanti. Tapi jika sering
bermalasan, tertidur di kelas dan tidak mengikuti kegiatan pondok seperti Hari,
itulah yang menjadi masalah.
Hari tampak
seperti orang yang dililit hutang. Ia tidak menemukan titik terang untuk
membayarnya. Berkali-kali ia menunduk di atas sebuah buku, namun pikirannya
entah ke mana. Makan dan minum sudah tidak bernafsu. Namun tubuh tambunnya
tidak berubah, itu keturunan. Dari sekian banyak teman-temannya, hanya satu dua
yang bercakap dengannya. Rasa rindu yang berlebihan itu membuatnya sulit
bergerak.
Itulah bahasa rindu
yang ada di hati Hari.
Namanya Yasin,
temannya Hari. Ia berbeda dalam menyikapi sebuah kerinduan. Katika rasa rindu
itu menerpanya di pondok, ia lampiaskan dengan belajar yang ganas. Satu detik
saja ia lepas dari buku atau Al-qur’an di tangannya, ia langsung teringat orang
tua. Belajar adalah amanah dari orang tuanya. Rindu itu terobati ketika Yasin
melaksanakan amanahnya. Ia serasa dekat, serasa dipeluk oleh orang tuanya. Ia
yakin bahwa dengan melaksanakan amanahnya, orang tuanya akan tersenyum.
Itulah bahasa
rindu yang ada di kamus Yasin, rindu yang menginspirasi.
Amir? Ia tak begitu
kenal dengan bahasa rindu. Setahunya rindu hanya satu dari sekian rasa dalam
hidupnya yang tak berlabuh lama di hatinya. Rindu hanya sebatas rasa kangen
setelah lama tidak bertemu. Amir sangat mudah menepis rindu karena rasa rindu
itu tak akan mendatangkan apa yang dirindukan. Hanya buang-buang waktu saja.
Lagipula pada hakikatnya kita tidaklah sendirian. Bahkan ketika kamu merasa terasingkan
dan merasa hanya kau yang ada di dunia, engkau pun tak sendirian. Manusia pada
mualnya adalah sendirian dan akan kembali dalam keadaan sendirian. Mengapa
harus menyimpan rindu?
---0---

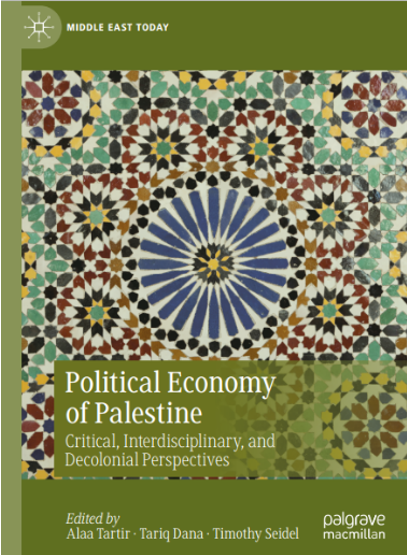


Comments
Post a Comment