Dari Persamaan Menuju Persatuan
Dari Persamaan Menuju Persatuan
Oleh : Firdan Fadlan Sidik
Islam adalah agama mayoritas yang
memiliki pengaruh kuat dan kontribusi
yang banyak terhadap sejarah di Indonesia. Islam mempunyai magnet kekuatan di mana kedamaian, ketenangan dan
ketentraman dapat diciptakan dan dirasakan. Islam yang moderat dan rahmatan lil’alamin tampak tercermin
dalam dunia dakwah Islam, khususnya Indonesia yang terkenal dengan dakwah tanpa
pertumpahan darah. Sejarah walisongo menjadi panutan para ulama Indonesia untuk
berdakwah, yaitu dakwah kultural di mana Islam tidak menyingkirkan budaya namun
justru sebaliknya. Islam yang relevan terhadap segala zaman dan berbagai tempat
membuat kedatangannya selalu disambut baik oleh budaya dan tradisi masyarakat.
Ia tidak merombak-rombak tatanan masyarakat dan tidak menjajah eksistensi budaya lokal. Inilah yang membuat ciri
khas Islam Indonesia di mata luar dengan peradaban Islam damai tanpa gejolak
perpecahan dan pertumpahan darah.
Islam di Indonesia patut dijadikan
sebagai rujukan negara dengan tingkat tolerasni tinggi. Pemerintah Indonesia
memberi jaminan kepada setiap golongan masyarakat untuk memeluk kepercayaannya
dengan aman dan dilindungi undang- undang. Tidak ada diktator mayoritas dan
tirani minoritas. Semua agama dituntut untuk saling menghormati agama lain,
menghargai hak dan kewajiban masing- masing, di mana hak seseorang dibatasi
oleh hak orang lain. Di antara prestasi Indonesia dalam hal kerukunan umat
beragama adalah penghargaan World
Statesman Award dari organisasi nirlaba Appeal
of Conscience Foundation (ACF) asal Amerika Serikat pada masa presiden
Susilo Bambang Yudhoyono. Penghargaan ini diberikan atas keberhasilan presiden SBY dalam menciptakan kerukunan antar umat
beragama di Indonesia. Agama Buddha
yang jumlah pemeluknya hanya 1% dari jumlah
penduduk Indonesia pun hari rayanya
dijadikan sebagai hari libur nasional. Adapun hari raya Idul Fitri di
negara minoritas Islam seperti Thailand dan Myanmar tidak diakui hari rayanya.
Keberagaman agama di Indonesia sangat sejuk dipandang mata. Tidak asing lagi bagi kita melihat
persahabatan antara seorang
Muslim, Kristen dan Buddha dari suku
Jawa, Batak, Sunda, Minang dan Tiongkok yang awet tanpa pertikaian. Grace
Olivi Sihombing, seorang mahasiswi bersuku Batak merasa
nyaman bersahabat dengan mereka. Diatherman Anggen pun merasa senang walaupun
dirinya berkumpul bersama rekan kerjanya yang mayoritas Muslim. Kejadian
sepasang pengantin Kristen yang akan menikah di gereja Katedral dipayungi oleh
seorang Muslim yang mengikuti aksi 212 dan pasukan pun memberi jalan untuk
pengantin lewat. 150 orang pemuda Nasrani yang turun tangan menjaga ketertiban
shalat Ied di Kabupaten Puncak,
Papua adalah realita
yang sangat mengaharukan. Tiga tempat ibadah
yang berdiri berdampingan yaitu klenteng Shen Mu Miaw, pura Jagadnatha Surya Kencana dan vihara di Tanjung Bunga, Kota Pangkalpinang
menjadi pemandangan indah selain
pemandangan perbukitan hijau
yang menyejukkan mata. Dan masih banyak lagi potret pemandangan pluralitas Indonesia yang sejuk lainnya.
Akar masalah
Indonesia sudah dipandang dewasa dalam
menyikapi keragaman agama dengan diperkuat oleh beberapa penghargaan dunia dan
realita yang kita lihat di masyarakat.
Tidak ada masalah kronis dalam hal ini. Namun ada hal lain yang terabaikan,
yaitu konflik internal agama itu sendiri yang justru masalahnya akan berujung
kronis. Suatu umat beragama yang sama tentu mempunyai tujuan dan sistem
beribadah yang sama. Perbedaan di dalamnya pun tidak lagi disebut aneh karena
akal manusia memang terbatas dalam memahami wahyu Tuhan. Kita tidak dapat
memungkiri bahwa pemahaman agama Tuhan tidak akan pernah ditangkap secara
sempurna oleh akal manusia. Alhasil perbedaan pun menjadi fitrah manusia dan
fitrah agama. Suatu golongan bisa saja menganggap amalan ini baik dan beriwayat
mutawatir. Dalam perspektif golongan lain mungkin dianggap tidak. Sebenarnya
hal ini tidak perlu diresahkan masyarakat umat beragama. Namun karena kedangkalan ilmu, klaim dirinya
paling benar pun merasuki jiwa mereka dan pertikaianpun terjadi.
Strategi untuk menumpahkan perpecahan
yang muktahir adalah dengan menghadirkan konflik internal agama. Sejarah telah
membuktikan hal ini. Portugis mencampurtangani urusan internal Kerajaan
Ternate. Sementara Spanyol mengintervensi urusan Kerajaan Tidore. Pertikaian
pun terjadi di antara dua kerajaan itu. Mereka lupa dengan identitas
kesamaannya sendiri, yaitu sama-sama
kerajaan Islam. Ambisi kekuasaan, harta dan tahta telah
membutakannya sehingga peperanganpun bergejolak dan pihak luar tertawa-tawa
menyaksikannya bagaikan mengasuh dua bocah tanpa dosa. Sejarah telah memberi
aba-aba untuk tidak mengedepankan hawa nafsu dan senantiasa jeli terhadap
jebakan-jebakan yang menghalang.
Islam sejak zaman sepeninggal Nabi
Muhammad SAW memang dibangun berdasarkan pertikaian demi pertikaian. Konflik
dan kekerasan hampir
tidak pernah mereda dan
menjadi fenomena kesejarahan. Perbedaan paham dan kepentingan kelompok untuk
memperjuangkan kekuasaan menjadi pemicu terjadinya perpecahan. Adapun di
Indonesia, walaupun terdapat ormas-ormas Islam, namun tidaklah separah
konflik yang terjadi
di negara lain. Secara garis besar terdapat
dua golongan ormas Islam di Indonesia, yaitu golongan muslim puritan dan
muslim kultural. Muslim puritan adalah kelompok muslim yang menganutt paham
puritanisme, yaitu paham yang berusaha memurnikan ajaran Islam dari pengaruh
luar (termasuk budaya) baik dalam bentuk keyakinan, pemikiran maupun praktik
keagamaan. Organisasi yang bercorak seperti ini misalnya Muhammadiyah, PERSIS,
jamaah salafi, MTA dan jamaah Tabligh. Sedangkan muslim kultural adalah muslim
yang memandang budaya sebagai sarana berlangsungnya transformasi agama.
Terutama di Pulau Jawa yang banyak diekspresikan melalui tradisi yang telah
membudaya. Golongan muslim ini yang paling terkenal adalah Nahdatul Ulama (NU).
Di antara dua tipe ormas ini dapat
ditarik dua golongan ormas yang paling besar dan berpengaruh di Indonesia,
yaitu Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama (NU). Perbedaan-perbedaan yang ada
mengakibatkan adanya jarak yang mencolok
antara Muhammadiyah dan NU. Terlebih masyarakat awam agama yang mudah
menjustifikasi bid’ah terhadap amalan Nahdiyyin,
maupun sebaliknya mengecam tidak mengikuti sunnah Rasul terhadap Muhammadiyah.
Seperti yang terjadi di Wonokromo,
Bantul. Kehadiran seseorang yang bergolongan Muhammadiyah di tengah masyarakat NU menghasilkan diskriminasi sosial. Terlebih pada tahun 2002 ketika sedang terjadi pemilihan
kepala desa. Hak suara pun sudah condong kepada golongan.
Dalam perspektif psikologi sosial,
terjadinya aksi ketidakadilan di masyarakat
berasal dari antagonisme kelompok. Menurut Taylor1 antagonisme
kelompok tampak ketika anggota satu kelompok (in group) menunjukkan sikap negatif terhadap anggota kelompok lain (out group). Antagonisme kelompok
memiliki tiga komponen yang saling
terkait, yaitu stereotip (stereotype), prasangka (prejudice), dan diskriminasi (discrimination).
Prasangka merupakan aspek yang paling destruktif dari perilaku manusia dan
sering menimbulkan tindakan yang mengerikan.
Prasangka (prejudice) adalah sebuah sikap yang biasanya bersifat negatif yang
ditujukan kepada anggota kelompok lain. Menurut Sears2 prasangka
didefinisikan sebagai persepsi orang tentang seseorang atau kelompok lain, dan
sikap serta perilakunya terhadap mereka. Newcom3 mendefinisikan
prasangka sebagai sikap yang tidak baik dan dapat dianggap sebagai suatu
predisposisi untuk mempersepsi, berpikir, merasa dan bertindak dengan cara-cara
yang “menentang” atau “mendekati” orang
lain, terurama sesama
anggota kelompok. Beberapa
definisi yang diungkapkan para ahli tersebut nampaknya ada kesamaan
bahwa prasangka merupakan sikap sosial yang biasanya bersifat negatif, objek
prasangkanya orang atau kelompok lain, dan sikapnya didasarkan pada keanggotaan
suatu kelompok. Bentuk prasangka dapat terwujud dalam : pertama, stereotip, yaitu pemberian sifat
tertentu terhadap seseorang berdasarkan kategori yang bersifat subjektif hanya karena berasal dari kelompok lain.
Kedua, jarak sosial, yaitu perasaan yang memisahkan seseorang atau kelompok
tertentu berdasarkan pada tingkat penerimaan tertentu, seperti ketidaksediaan
untuk menikah dengan etnik lain, ketidakmauan menjadikan etnik lain dalam
anggota klubnya, ketidakmauan menerima sebagai tetangga dan rekan kerja.
Permasalahan yang terjadi di Indonesia
adalah prasangka agama di mana sering menimbulkan konflik berkepanjangan, khususnya
konflik sesama agama yang memiliki pemahaman atau organisasi keagamaan yang
berbeda. Prasangka agama yang terjadi dalam Islam terjadi antara muslim
tradisional dan muslim
1 Shelley E Taylor,dkk, Psikologi Sosial (terj.) Jakarta:Kencana
2009 h.210
2 Sears D. O,. Psikologi Sosial, Jilid II (terj.), (Jakarta:Salemba Humanika,
2009) h.226
3 Newcomb T.M., Psikologi Sosial, (Bandung: Diponegoro,1985), h.564
modern,
antara muslim moderat dan muslim radikal, antara muslim kultural dan muslim
puritan.
Dalam realita sosial, prasangka tidak
mungkin bisa dihapus sama sekali. Upaya yang dapat dilakukan untuk
mengendalikan dan mengurangi prasangka di antaranya adalah belajar untuk tidak
membenci, meningkatkan intensitas kontak antar
kelompok, dan rekategorisasi atau melakukan perubahan batas antara ingroup
dan outgroup-nya. Dengan kata
lain tidak ada lagi kata “us (kami)
dan they (mereka)” tetapi berubah
menjadu “we (kita)”. Terkait hal ini
(keberagaman Islam di Indonesia), Presiden
Gus Dur menyikapi
dan menjawabnya dengan
ringan : Yang
jelas sama, jangan dibeda-bedakan. Yang jelas beda, jangan di sama-samakan.
Gitu aja kok repot. Kata-kata beliau sangat menginspirasi berbagai
kalangan, khususnya umat Islam.
Pemaparan beliau dapat kita pahami
bahwa perbedaan kecil jangan terlalu diperhatikan kerena
akan menghasilkan gesekan yang cukup kuat di antara dua golongan yang mempunyai suatu persamaan mendasar.
Fokus kita tidak pada itu, melainkan pada
penyinergian kekuatan antara berbagai kelompok dan ormas Islam untuk menghalau
kekuatan dari luar. Jangan sampai kita sibuk sendiri berkutat dalam situasi
internal agama sendiri sehingga membuat
agama lain tersenyum-senyum bahagia melihat musuhnya bertengkar sendiri dan
misi mereka terlancarkan. Lain halnya
jika bersatu dalam perbedaan. Berbeda memang identik dengan kejelekan
dan kontoversi. Namun jika perbedaan
itu disatukan akan menjadi
sebuah kekuatan tersendiri karena dengan perbedaan itulah kekurangan masing-
masing akan terlengkapi.
Inilah yang menjadi PR bagi umat Islam
untuk bersatu. Karena betapapun banyaknya umat Islam
di Indonesia akan terlihat kecil jika dikotak-kotakan dengan perbedaan dan terputusnya tali silaturahim. Dengan
berazaskan persamaan tujuan, sebuh organisasi dapat berjalan dengan baik.
Dengan berdasarkan persamaan derajat, umat manusia dapat memperjuangkan haknya.
Begitupun Islam. Dengan berlandaskan persamaan aqidah akan menumbuhkan
persatuan, menyinergikan kekuatan dan membumikan kedamaian.
Referensi
Jurnal
Islam IAIN Walisongo
http://diglib.uin-suka.ac.id/1084/ diunggah pada hari Selasa,
14/11/2017 pukul 11:41
http://www.infoyunik.com/2016/08/inilah-surah-yang-buatumar-bin-
khattab.html?m=1 diunggah pada hari Minggu, 12/11/2017 pukul 04:46
http://m.detik.com/news/berita/d-3349166/menyejukan-potret-toleransi-beragama- dari-samarinda-hingga-papua/5#detailfoto diunggah pada hari Minggu, 12/11/2017 pukul 06:06

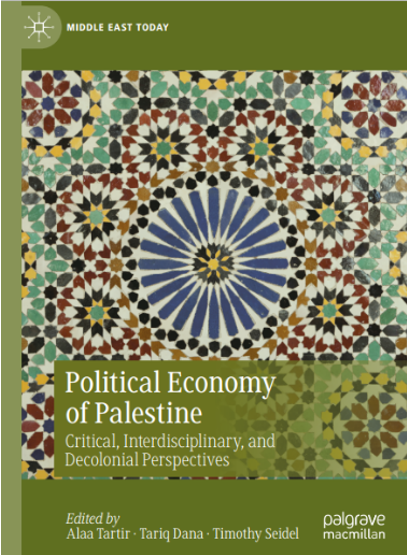


Comments
Post a Comment