Harmoni di Kota Toleransi
Kota Salatiga adalah kota pengembaraanku selama kuliah S1. Di kota itu
terdapat dua kampus besar, yaitu Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW) dan
Universitas Islam Negeri (UIN) Salatiga. Kampus Kristen di Salatiga itu merupakan
kampus yang bersejarah. Kehadirannya tidak terlepas dari estafet misionaris
Kristen pada era kolonial.
Berbicara prestasi Kota Salatiga yang berkali-kali dinobatkan sebagai
Kota Toleransi, sebetulnya sudah terjadi sejak era kolonial. Sebagai mahasiswa
sejarah, saya pernah meneliti sejarah sosial masyarakat Muslim dan Kristen era
kolonial di Kota Salatiga. Di samping itu, saya juga aktif berdiskusi dengan
kawan saya, sejarawan yang beragama Kristen, asli kota Salatiga.
Sebagai kota tua, Salatiga telah merangkai sejarah toleransinya dengan
ditandai tumbuh suburnya misionaris (zending) Kristen dan bersandingan dengan peradaban subur ulama dan santri di
pinggiran Kota Salatiga. Kecamatan Tingkir merupakan wilayah Salatiga yang
dikenal dengan basis santri dan tempat lahirnya ulama-ulama terkenal. Di sana
terdapat makam KH. Abdul Wahid, kakek buyut Gus Dur. Juga beberapa ulama otoritatif
lain seperti ulama ahli falak: KH. Zubair Umar Jailani, ulama Kristologi: KH.
Humaidi Soleh, dan ulama pejuang: KH. Damarjati. Sejak era kolonial, masyarakat
Muslim ditempatkan di Tingkir, pinggiran kota. Sedangkan wilayah kota dihuni
oleh orang-orang Eropa yang kebijakannya selalu diskriminatif.
Ketika saya memaparkan penelitian saya soal Islam, dan kawan saya soal
Kristen, kami sepakat dalam satu hal bahwa di Salatiga tidak terdapat
pergesekan sosial-masyarakat meskipun sejak zaman dahulu hingga sekarang
penduduk Salatiga sangat multi-kultur, multi-etnis, dan multi-agama. Pergesekan
kecil tentu ada, dan kami menginterpretasikannya sebagai sebuah anomali dan
oknum semata karena nyatanya pergesekan itu tidak berdampak signifikan.
Lebih mengerucut lagi, suasana toleransi sangat mendarah daging bagi
masyarakat Salatiga. Kota itu seperti memang seolah dilahirkan untuk berbeda
dalam banyak hal. Di lingkungan sekitar kampus saya, UIN Salatiga, mayoritas
penduduknya adalah umat Kristen. Kami mahasiswa UIN selalu berjalan melewati
rumah mereka tatkala berangkat pengajian ke masjid kampus. Sebagai pendatang,
saya kagum dengan keramahan mereka yang selalu menyapa dan menebar senyum
ketika berpapasan. Khususnya kepada pemilik warung depan kampus yang sangat
terbuka dan selalu mengajak bercerita para pembelinya yang mayoritas mahasiswa
UIN.
Pada tataran kampus, baik UIN maupun UKSW, selalu mewacanakan
pentingnya toleransi dan menyelenggarakan seminar tentang toleransi. Misalnya
di UIN Salatiga. Pada tahun 2018 menghadirkan Cak Nun, sosok ulama dan
budayawan, dalam kegiatan Orientasi Mahasiswa Baru. Cak Nun mengungkapkan kekagumannya
pada Kota Salatiga sehingga beliau menjuluki Kota Salatiga sebagai miniatur
Kota Madinah. Keberhasilan Nabi Muhammad dalam mengelola masyarakat Madinah
yang majemuk itu dinilainya berhasil diterapkan di Kota Salatiga.
Mahasiswa pun sangat apresiatif dan menguatkan nilai toleransi itu dengan
mengadakan diskusi ilmiah. Saya aktif di komunitas Youth
Interfaith Peacemaker Community (YIPC), sebuah komunitas
Muslim-Kristen yang menyuarakan narasi perdamaian. Tidak hanya teori, komunitas
itu juga aktif berkegiatan sosial umat Islam dan Kristen, tidak pada perayaan
ibadah masing-masing.
Resep Toleransi dari Kota Salatiga
Saya beruntung karena berkesempatan untuk meneliti kota yang unik ini.
Kota kolonial berusia 1.272 tahun ini menyimpan sejarah toleransi yang
mendalam. Penelitian saya berkesimpulan pada ungkapan Gus Dur: “Semakin tinggi ilmu
seseorang, maka semakin besar rasa toleransinya.”
Peran tokoh agama dalam membangun kota toleransi sangatlah penting.
Sebagai rujukan umat, pemuka agama harus memiliki wawasan yang luas dan
komprehensif terhadap suatu agama.
Tokoh agama yang saya teliti adalah KH. Humaidi Soleh, ulama penting
Nahdlatul Ulama yang aktif berjejaring dengan tokoh kolonial Belanda dan
masyarakat Kristen. Ia mengabdi pada pemerintahan kolonial dan aktif bersosial
karena ia menjabat sebagai penghulu yang harus mengayomi kebutuhan masyarakat.
Demikianlah koran De Locomitief Belanda mewartakan beliau.
Dari informan lain saya menemukan dokumen berupa kitab Kristologi
berjudul al-Intishor wat Tarjih li Dini Shohih, kitab karangan KH Humaidi
Soleh yang diterbitkan di Mesir. Pengembaraan akademiknya dihabiskan di Mekah
selama 10 tahun dan Mesir selama 7 tahun. Buku ini merupakan pemikiran
mendalamnya soal agama Kristen setelah ia berdebat akademik dengan Paus di
Vatikan.
Ketika saya berdiskusi dengan kawan saya, sejarawan lokal Salatiga yang
beragama Kristen itu, dia menyebutkan bahwa sejak awal berkembangnya misionaris
zending Salatiga, tidak ada pemaksaan dan kekerasan sosial sebelum pembaptisan
warga lokal. Seorang pelopor misionaris bernama Elizabeth Jacoba Le Jolle-de Wildt menyebarkan misi Kristen melalui
pendidikan dan pelayanan ekonomi. Dokumen arsip di kantor KITLV Jakarta
menggambarkan adanya pendidikan umum bagi warga Salatiga yang diselenggarakan
oleh minionaris. Dengan demikian, dapat
disimpulkan bahwa pendekatan para misionaris Kristen Salatiga lebih bersifat
humanis.
Dengan perbandingan fakta sejarah itu, saya dan kawan saya akhirnya berkesimpulan bahwa salah satu resep toleransi adalah kehadiran pemuka agama yang berwawasan luas dan komprehensif. Dia pun mengutarakan bahwa tokoh Kristen Salatiga era kolonial sampai sekarang yang menggerakkan yayasan sosial Kristen di Salatiga merupakan tokoh cendekiawan yang atas kedalaman ilmunya itulah ia aktif mengayomi masyarakat tanpa pandang bulu. Semakin tinggi ilmu seseorang, semakin tidak ragu untuk bersikap toleran.
Penulis : Firdan Fadlan Sidik

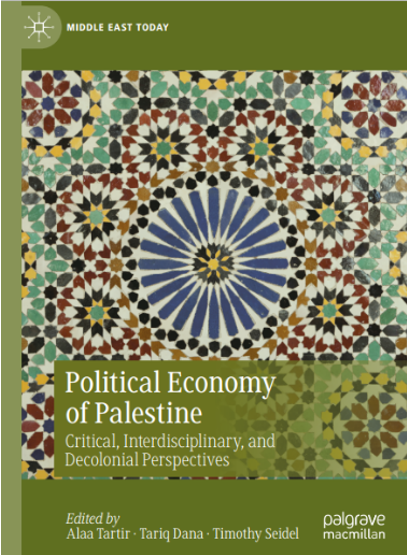


Comments
Post a Comment