Ber-Toleransi sejak dari Hati
Terkadang banyak orang yang memahami
suatu istilah dengan makna-makna yang ribet dan rumit. Sampai-sampai ia lupa
untuk menengok makna paling sederhana dan paling erat kaitannya dengan
sehari-hari.
Misalnya kata “toleransi”. Orang
melihat bahwa toleransi adalah sebuah istilah dalam interaksi sosial yang
bersifat rukun dan konstruktif di tengah perbedaan sosial. Ada beberapa
variabel penting di dalamnya, yaitu “interaksi sosial” dan “perbedaan.” Dari
pengertian ini lantas orang-orang berpikir bahwa toleransi hanya akan terjadi
di lingkungan sosial yang multikultural. Lantas, bagaimana dengan masyarakat
yang homogen? Apakah di daerah sana tidak mengenal kata toleransi?
Jika ditarik sudut pandang yang lebih
luas, maka dua variabel di atas akan mendapat pemaknaan yang lebih esensial dan
mendalam. Bahwa interaksi tidak hanya terjadi di alam sosial yang terbuka,
melainkan dari interaksi personal dengan dirinya sendiri. Tentu setiap orang
pernah dan sering berdebat dengan diri sendiri, bukan? Setiap orang pasti
melibatkan hati nuraninya untuk diajak berpendapat sebelum menentukan sikap.
Ada ego dan nurani yang selalu beradu pendapat. Ego kita selalu berusaha
mengiring pada hal-hal yang menguntungkan diri pribadi. Sementara nurani selalu
meniupkan jiwa sosial dan mempertimbangkan penerimaan orang lain.
Kemudian variabel “perbedaan” tidak
harus mencakup golongan sosial, ras, suku, agama, maupun politik yang berbeda.
Perbedaan itu sering kita temukan di sekitar kita dalam lingkup mikro yang
berkelindan. Tentu di sekeliling kita banyak sekali perbedaan-perbedaan yang
membuat kita harus berdebat dengan perbedaan itu. Perbedaan dengan kawan
persahabatan, perbedaan dengan pasangan, dan perbedaan lainnya. Cara untuk
“selesai” dengan perbedaan itu adalah dengan menggunakan konsep toleransi
dimana seseorang harus mampu melihat suatu objek dari sudut pandang lawan
bicara. Bersikukuh melihat suatu objek dari perspektifnya sendiri dan
menghiraukan perspektif orang lain adalah sebuah hal yang naif dan tidak
menyelesaikan masalah.
Ingat. Toleransi bukanlah hal yang
pasif. Hanya sekadar menghargai perbedaan tanpa ingin tahu apa yang dipandang
oleh orang lain saja tidak cukup. Toleransi pasif inilah yang kemudian dijuluki
toleransi yang murah. Toleransi yang sesungguhnya adalah kita harus sampai pada
memahami apa yang orang lain pahami hingga membuat kita berbeda.
Ada sebuah buku menarik berjudul Costly
Tolerance. Buku ini menggambarkan fenomena toleransi dalam kehidupan dengan
sepenuh pemaknaan toleransi yang utuh. Penulis mengatakan bahwa toleransi
adalah tentang “mengatasi ego sendiri” seperti pada pepatah Maluku: “ale rasa
beta rasa”, yang artinya apa yang kamu rasakan, saya juga merasakan.
Toleransi dapat terjalin ketika
pluralisme menjadi struktur faktual realitas atau dengan kata lain menjadi
sebuah ideologi yang meyakini keberagaman sebagai sebuah fitrah kehidupan. Pemahaman
bahwa berbeda adalah sebuah keniscayaan membuat kita lebih yakin bahwa
toleransi adalah sebuah keharusan. Dan faktanya di lapangan juga demikian.
Semakin tinggi ilmu seseorang, ia akan semakin toleran. Demikianlah ungkapan
Gus Dur, sosok Presiden RI yang menjadi pahlawan bagi semua kalangan umat
beragama di Indonesia.
Nah, untuk memupuk jiwa toleransi
harus dimulai sejak hati. Artinya, kita harus mampu menerapkan nilai-nilai
toleransi di ruang-ruang yang paling dekat dengan kita. Di ruang keluarga,
ruang persahabatan, maupun ruang kerja. Ketika kita menjumpai perbedaan-perbedaan
di ruang-ruang itu, cobalah bersikap lebih bijak dengan memperluas perspektif
ketika melihat sesuatu. Libatkanlah hati dan pikiran kita untuk merasakan apa
yang hati mereka rasakan dan apa yang akal mereka pikirkan. Niscaya kita dapat
bersikap toleran menyikapi perbedaan itu.
Misalnya kita dihadapkan dengan “gap
education” atau kesenjangan pendidikan antara orang tua dan anak. Orang tua
lahir dari orisinalitas kehidupan desa dan non pendidikan tinggi, sementara
anaknya berkelana jauh dan berpendidikan tinggi. Ketika pulang kampung,
pertemuan dua entitas yang gap education ini pasti bergejolak. Nah, pada
ruang keluarga inilah yang membutuhkan praktik toleransi yang sesungguhnya.
Contoh lain, misalnya dalam relasi kerja.
Setiap orang memiliki karakter yang berbeda-beda yang terbentuk dari genetika,
pendidikan, dan lingkungan hidupnya. Misalnya si Koleris (tegas dan berkemauan
keras) bertemu dengan si Plegmatis (cuek dan kalem) dalam sebuah lingkungan
kerja. Ketika sebuah kepanitiaan mengharuskan mereka bertemu dan bekerja dalam
tim, maka mau tiak mau mereka harus menyatukan persepsi agar target dan job
mereka tercapai. Padahal di sisi lain, karakter mereka berlawanan dan memiliki
kemungkinan yang destruktif. Pada kondisi seperti inilah teori toleransi itu
perlu di praktikkan sehingga kekurangan yang mereka miliki tidak menghambat
kerja dan kelebihan dari mereka diharmonisasikan.
Lebih daripada itu, toleransi juga
harus diaplikasikan dalam ruang-ruang persamaan, tidak mesti harus selalu dalam
perbedaan. Misalnya dalam kegiatan keagamaan. Setiap agama pasti memiliki paham
dan mazhab yang berbeda sebagai sebuah keniscayaan bahwa manusia memiliki akal
dan keterbatasan untuk memahami sebuah agama yang turun dari Tuhan. Maka bertoleransi
sesama warga Muslim yang berbeda mazhab (ataupun ormas) juga merupakan sebuah
keharusan. Jangan sampai alergi atau sensitif melihat perbedaan dalam hal
ibadah yang bersifat furu’iyah (bukan hal mendasar). Kita yang misalnya
berpaham harus memakai do’a Qunut dalam sholat Subuh jangan sampai agresif atau
sensitif melihat saudara kita yang tidak memakai Qunut.
Masih banyak sisi kehidupan ini yang
menuntut kita untuk mengharmonisasi perbedaan yang kita hadapi. Maka
menumbuhkan jiwa-jiwa toleran itu sebetulnya harus dipupuk sejak dari hati. Toleransi
harus dipupuk sejak dalam persamaan, tidak mesti dalam perbedaan. Bertoleransi
di ranah global dan luas tidak akan tumbuh hebat tanpa bertoleransi dengan diri
kita sendiri, dari hati kita sendiri.
Penulis : Firdan Fadlan Sidik

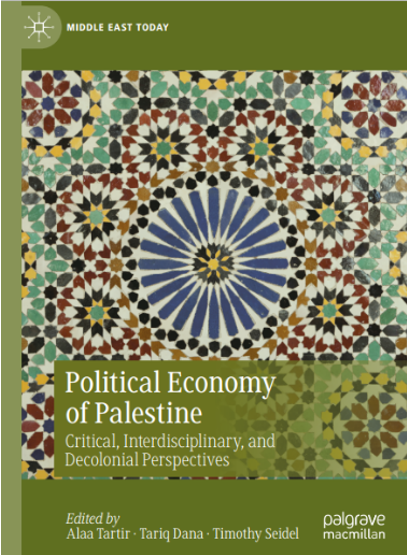


Comments
Post a Comment