Pintar itu Luka
Pintar itu Luka
Oleh : Fadlan S
Gelap menyelimuti malam yang pekat di pengujung November kota
Salatiga. Seorang pemuda termenung di atas meja memandang pigura foto orang
tuanya. Malam itu, asrama masih hening menyisakan geriknya di atas sajadah.
Selepas sholat ia memandang foto itu lekat-lekat. Sepucuk semangat
tertiup dari foto itu bagaikan bunga disirami air dan lantas mekar. Seutas
senyum terukir di bibirnya membuat air bekas wudhu itu menetes ke dagunya
hingga jenggot tipisnya.
“Baik-baik di sana ya Pak, Mah.” Ucap Ayyubi dalam benaknya.
Lantas ia lanjutkan keluh kesahnya kepada Sang Maha Kuasa dalam
sujudnya.
“Ya Allah, berikanlah hamba pilihan yang lebih maslahat antara
kuliah ke Turki atau terus mengabdi di pondok. Ya Allah, hamba yakin keduanya
baik menurut hamba. Namun hamba harus memilih salah satunya. Jika itu baik
menurut-Mu, terangkahlah dan mudahkanlah segara urusannya. Aamiin ya rabbal
‘alamiin...”
Dialah Ayyubi, seorang santri takhosus di pesantren Al-Jami’ah.
Kelulusannya dalam seleksi beasiswa kuliah S2 di Turki membuatnya semakin
gundah dalam menentukan langkah. Ia harus mempertimbangkan hal lain, yaitu
kepercayaan kyai kepadanya untuk menjadi musyrif[1]asrama.
Kebahasaannya yang tidak diragukan, kefasihan Al-Qur’annya yang bersertifikasi
dari ustadz, serta keindahan pita suaranya dalam mengaji dan saat menjadi imam
membuat kyai lantas memercayakan pondok kepadanya. Kini ia berada di puncak dilema,
antara takdzim dan cita-cita yang harus dipilih salah satu.
Mentari semakin berseri. Cahayanya tampak di balik kubah masjid Ath-Thayyar.
Para santri berbondong-bondong menuju masjid untuk menegakkan takbir duha.
Ayyubi sudah mulai dalam kesibukannya di kantor pesantren, tidak jauh dari
masjid. Sebuah pesan masuk ke ponselnya lantas ia buka.
Assalamu’alaikum warahmatullah.. Afwan mas Ayyubi. Kami dari
panitia seminar akan menjemput mas ke Pondok Al-Jami’ah. Sarapan pagi dan kamar
penginapan sudah kami siapkan. Nanti kami akan menuju kantor mas Ayyubi. Terima
kasih mas, afwan mengganggu.
“Astagfirullah, aku lupa kalau harus mengisi seminar.” Pesan
itu seolah menjadi alarm bagi kekhilafan dirinya.
Ayyubi diundang oleh Kemenag untuk mengisi seminar dan diskudi
keagamaan di salah satu perguruan tinggi. Beruntunglah panitia memberi aba-aba
lewat SMS. Lantas ia mempersiapkan materi power point berkenaan dengan
tema seminar. Tampaknya ia tak butuh waktu lama dalam membuat slide power
point karena sudah berkali-kali ia diundang untuk mengisi seminar. Setelah
meraih prestasi sebagai mahasisiwa berprestasi Nasional, ia sering disoroti
banyak pihak. Berbagai seminar, diskusi dan konferensi seringkali ia diundang
menjadi pemateri. Dalam menyiapkan materi seminar kali ini, ia cukup mengutip
dari mozaik-mozaik presentasinya yang lalu.
Sebuah mobil innova putih terparkir di halaman pesantren dan
seorang pria berjas rapi menjemput Ayyubi di kantor. Ia mengajak Badrun, salah
satu santrinya untuk menemaninya sekaligus delegasi pesantren dalam seminar. Selama
perjalanan, ia disambut dengan perbincangan ramah dari panitia. Mobil itu melaju menuju sebuah
hotel berbintang.
“Mas, saya tinggal dulu ya. Selamat beristirahat. Seminarnya berlokasi
di convention center hotel ini. Jika acaranya hendak dimulai, akan saya
kabari lagi. Permisi mas.”
Alih-alih merebahkan badan, ia mengambil air wudhu untuk menegakkan
takbir duha. Tampak lama sekali ia bersujud, begitupun berdo’a.
Selepas sholat, ia dan Badrun bergegas untuk sarapan di restoran
hotel yang begitu indah bersandingan dengan kolam renang dan taman. Mereka
duduk di sebuah meja menghadap taman.
“Mas, enak ya kalau jadi ‘orang’. Hidupnya enak, terjamin, disegani
orang banyak,,,,”
Ayyubi hanya tersenyum.
“Tidak juga Badrun. Pintar itu sebuah luka.”
“Luka? Mas Ayyubi sastrawi banget kata-katanya. Jabarkan dong mas.”
Pinta Badrun.
“Habiskan makannya dulu. Nanti lanjut ngobrol..”
Setelah santap sarapan habis tak tersisa, Ayyubi menjawab request
dari Badrun.
“Kamu lihat pohon tinggi nan rindang itu di bawah! Angin kota
menampar daun-daunnya. Adakalanya harus terjatuh ke bawah karena terseleksi alam.
Adakalanya ditebang secara paksa karena sudah gondrong dan menghalangi jalanan
kota. Di balik keindahan pohon yang berbuah, terdapat banyak sekali tantangan
yang menghalanginya.”
Ayyubi menyela perbincangan dengan seteguk cokelat hangat.
“Beda halnya dengan bagian akar pohon itu. Dia letaknya di bawah,
tidak terlihat, tidak ada hambatan. Tapi tidak juga banyak dicari-cari orang
karena akarnya. Alam yang Allah ciptakan adalah sarana untuk mengambil
pelajaran dan ‘ibrah. Kita ibaratkan karier kehidupan juga dengan sebuah
pohon yang semakin tinggi pohon itu, semakin banyak rintangan yang dihadapinya.
Dan sebaliknya, jika kita hanya mencukupkan diri untuk menjadi akar, tidak ada
rintangan di depan kita. Tapi tidak ada juga manfaat yang kita tebar kepada
orang lain. Bahkan kita malah sering diinjak orang.”
Badrun menyimaknya dengan baik.
“Ustadz yang lain juga pernah meyampaikan di kelas, bukan ?”
“Iya mas, pernah.”
“Seorang akademisi yang pintar, dalam realitanya ia memikul sebuah
luka yang teramat besar. Luka itu ada di dalam ini Bad.”
Ayyubi memegang dadanya.
“Jika apa yang ada di dalam dada ini merasa ‘ujub, takabbur,
hingga lupa akan siapa yang telah membuatnya sukses, maka ia akan lebih jelek
kedudukannya daripada orang yang bodoh yang tahu diri.”
Ayyubi terdiam, memberikan kesempatan Badrun untuk merespon.
“Betul juga ya mas. Kebanyakan orang yang sudah menjadi ‘orang’ itu
malah lupa diri mas. Beda dari sebelumnya. Dari cara jalannya, ngomongnya,
tingkah lakunya, semuanya berubah. Saya juga heran.”
“Iya, betul Bad. Kamu juga sudah bisa mengamati. Di luar sana
banyak. Itu merupakan bagian dari lukanya seseorang yang pintar, yaitu
tantangan hati. Disanjung-sanjung, dipuji, dimuliakan banyak orang, disegani
masyarakat, diberikan posisi yang mulia, dan masih banyak bentuk penghormatan
yang sebenarnya ini adalah luka bagi pemiliknya. Ia sangat berat memikul beban
pujian yang rentan menggores hati untuk menjadi sombong.”
“Tapi mas, bukannya kemuliaan dan penghargaan derajat bagi orang
pintar itu memang keniscaayan sebagaimana yang difirmankan Allah dalam surat
Al-mujadilah ayat 11 ?” Tanya Badrun.
“Betul sekali Bad. Keistimewaan derajat bagi orang yang berilmu itu
tidak hanya di akhirat melainkan juga di dunia. Namun, jika kita gagal dalam
mengemban kemuliaan derajat di dunia, mungkin akan gagal mendapatkan kemuliaan
di akhirat.”
“Maksudnya mas ?”
Ayyubi menyeruput kembali cokelat hangatnya yang sudah dingin lalu
kembali berbicara. Susul Badrun melakukan hal serupa.
“Jika seseorang yang berilmu itu lantas sombong dan lupa diri
kepada Dzat yang telah membuatnya pintar dan menitipkan secuil ilmu dari
pemiliknya, maka hanguslah sudah kemuliaan di akhirat karena surga tidak
menerima orang yang memiliki rasa sombong walaupun sebiji dzarrah[2].”
Badrun menganggguk paham. Ayyubi melihat jam tangannya.
“Sudah kenyang?” Ia menebarkan pandangan ke piring-piring dan
gelas-gelas yang nampak sudah kosong bersih.
“Sudah mas, alhamdulillah.”
“Lanjut nanti ya bincang-bincangnya. Ayo kita bergegas pulang.
Sebentar lagi seminarnya akan segera dimulai.”
Cahaya mentari tampak semakin meninggi. Tepat pukul 9 nanti, Ayyubi
harus sudah stand by di convention center hotel. Badrun selalu sigap
menemani gurunya itu ke manapun pergi. Seperti biasa, dia selalu siap dengan
buku kecil, pulpen, dan kartu pers yang dipasang di saku kemejanya.
“Saudara-saudara, mengapa kitab karangan para ulama salaf sampai
saat ini masih eksis dibaca masyarakat dan tidak hilang ditelan zaman? Karena manuskrip
sejarah Islam karangan para ulama dalam pembuatannya melalui proses yang tidak
sederhana. Para ulama tidak sembarangan dalam menulis. Beliau melalukan shalat
terlebih dahulu sebelum menulis. Dan untuk menyelesaikan sebuah karyaa, beliau
berpuasa selama 1 tahun. Dan dalam setiap menulis, beliau berwudhu serta sholat
terlebih dahulu.“
Ayyubi memaparkan pengalaman-pengalamannya dalam dunia kepenulisan
dan penelitian sejarah. Ia terbarkan kepingan demi kepingan perjuangannya dalam
menggeluti kariernya. Badrun dan peserta seminar lainnya terkagum-kagum melihat
orasinya yang santai dan komunikatif.
Seusai seminar, mereka kembali berbincang-bincang. Dalam eloknya
senja di tepi kota, ia menuju restoran hotel yang berada di lantai tujuh dengan
pemandangan semi terbuka berdinding kaca.
“Mas, lanjut obrolan kemarin dong.”
Di depan hidangan makan malam, mereka kembali berbincang.
“Berkumpul dengan keluarga itu adalah hal yang didambakan setiap
orang. Nah, si lumbung ilmu itu punya luka yang berat. Waktu yang dimilikinya
terkena serangan anemia-time atau kekurangan waktu. “
“Anemia-time ?”
Badrun seketika tertawa mendengarnya. Mereka tertawa.
“Iya, bahasanya gitu lah menurutku. Si lumbung ilmu harus rela
mengorbankan banyak waktunya demi umat yang setiap minggu pasti full dengan
undangan. Tidak mungkin ia menolak, sementara ilmu yang didapat itu mempunyai
amanah tersendiri untuk disampaikan kepada orang lain.”
“Belum lagi ketika diundang, pasti banyak tamu yang menyanjunginya.
Diberi tempat first priority, jamuan mewah, dan penghormatan lainnya.
Apakah itu tidak cukup membuatmu merasa senang ? Tentu, lebih dari sekedar
senang. Dan inilah yang dimaksud dengan luka hyper-happy.”
“Hyper-happy ?”
Badrun kembali tertawa. Istilah-istilah bikinan gurunya itu cukup
kreatif dan menggelitik orang yang baru dengar.
“Wah, cukup berat juga ya menanggung luka si Pintar. Ada lagi mas
luka yang ditanggung ? Jangan-jangan ada kanker juga. Hahaha....”
“Eits, jangan salah. Ada kanker juga loh. Namanya itu kanker
kalbu.”
“Ada-ada aja mas. Saya sampai kebingungan mau nyocokin apa dengan
kata kanker.”
“Si Pintar itu menanggung luka kanker kalbu. Kalbu atau hatinya
digerogoti sama daging yang menggumpal bernama takabbur. Daging ini sebenarnya
tidak berbahaya jika kita mampu mengendalikannya. Namun jika kita kewalahan dan
terbuai dengan berbagai pujian, maka daging ini akan meningkat stadiumnya jadi
KRITIS, bahkan KOMA.”
“Sejak kapan sih mas pindah jurusan jadi kedokteran? Hahaha...”
Badrun meluapkan tawa.
“Bebas beristilah dong. Mulut, mulut siapa ? Hahaha.... pinjam
kata-katanya Andre pas melawak.”
“Puji itu milik siapa sih, Allah kan ? Nah, jika si Pintar ini
melahap pujian orang lain untuk dirinya sendiri, sungguh hinalah dia karena
telah memakan bukan hak seorang hamba. Jika pujian sudah ia lahap, ia akan lupa
diri, lupa akan siapa yang telah menitipkan ilmu kepada dirinya. Selama ia
lupa, selama itulah kankernya semakin ganas.”
Hotel mewah itu menjadi menjadi terlihat indah untuk kerenyahan
perbincangan mereka. Cahaya senja mebuat tubuhnya indah jika dibuatkan foto
siluet.
---0---

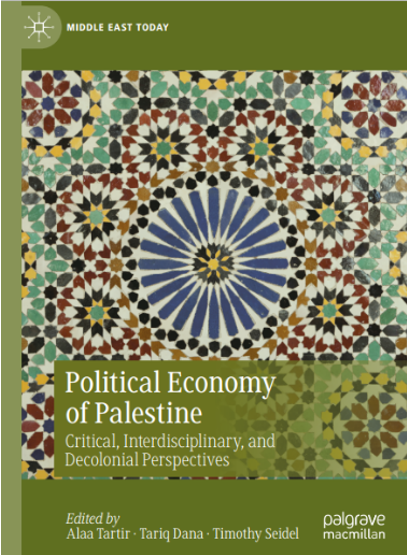


Comments
Post a Comment