Semanis Gethuk
“Semanis Getuk
– Firdan Fadlan Sidik”
Kejadian itu masih menyimpan jejak
luka yang membayangi setiap langkahku. Sudah sekian purnama pengembaraanku,
masih meninggalkan kepedihan yang dalam. Aku masih ingat. Waktu itu aku
menangkap guratan kesedihan di wajah ayah saat melepas kepergianku mencari
segembleng ilmu ke kota budaya, Solo. Anehnya, ia masih sempat melukiskan
senyum di bibirnya. Ayah kira aku tak tahu masalah yang menimpa saat itu.
Masalah yang membuat kecengenganku memuncak.
Aku masih ingat. Bunyi handphone
itu membangunkan tidur nyenyak ayah. Rupanya Wa Dadang menelpon ayah dan
berbincang basa-basi. Ia sempat meminta maaf mengganggu tidur ayah. Aku semakin
heran. Suara ayah di kamar sedikit mengganggu konsentrasi belajarku di ruang
tengah dan menyita perhatianku untuk mendengarnya.
“Jadi mobil itu mau kamu jual hanya
untuk biaya sekolah anakmu?” Bentak pemuda kaya raya itu dalam handphone yang
ayah keraskaan suaranya.
“Jangan habis-habisan nyekolahin
anak. Sudah tahu mobil itu harta paling berharga. Apakah tak bisa cari sekolah
lain yang lebih murah, bahkan gratis ?” Tambahnya.
“Ya, mobil carry tahun
1980-an itu mau saya jual dan sudah ada pembelinya. Cash. Siap dua belas
juta. Tujuh juta untuk biaya sekolah. Tiga juta bayar perbaikan mobil. Sisanya
bayar hutang.”
Suara ayah terkujur lemah kepada
kakaknya itu. Ia masih menyimpan takdzim kepadanya. Apa boleh buat. Selama ini
uwalah yang banyak membantu. Gubuk kecil tempat berteduh ini pun atas belas
kasih uwa. Tak jarang ia memberi makanan dan mainan untuk adikku. Lembaran rupiahpun
sering ia bekalkan untuk sekolahku. Terlalu banyak hutang budi jika ayah
kembali membentaknya.
“Yang penting anaknya rajin, pasti
bisa sekolah dimanapun. “
Kata-katanya menampar semangat ayah
untuk menyekolahkanku. Namun semangat ayah bagai karang yang tegak berdiri
dalam terjangan ombak, terpaan badai dan sengatan matahari yang tak kenal
kesah, tetap berdiri dalam pijakan sendiri. Jika langkah ayah sudah benar dan
tidak memadaratkan orang lain, kenapa tidak ? Menjadi tuli memang perlu dalam
hal ini.
“Iya, memang betul apa yang uwa
bicarakan. Sangat betul. Namun apakah ada sekolah taraf kantong saya yang bisa
mendapatkan fasilitas yang mumpuni? Apalagi anak saya ingin sekali tinggal di
pondok pesantren. Biaya makan dan pendidikan tiap bulannya menjadi beban saya
sebagai ayah untuk memperjuangkannya. Tak ada beban untuk uwa. “ Jawab ayah,
tegar.
“Sudahlah, janganlah melihat taraf
itu. Biar orang berkantong besar yang layak masuk pondok. Bukankah masih ada
MTs di desa dekat rumah? Murah dan dekat. Setaraf kamu, terlalu kejauhan
memikirkan pondok pesantren berbasis billingual itu.” Sahut uwa
mengerucutkan masalah.
“Belum lagi biaya transportasinya,
buku-buku, kitab kuning dan lain-lain. Gila kamu. Biaya masuk tujuh juta.
Transportasi pulang pergi Tasik-Solo tiga ratus ribu. Pikirmu terlalu jauh. Ya
sudah. Saya minta uang kembali mobil yang akan kamu jual.” Pintanya, ganas.
Semakin menegangkan. Mobil rusak uwa
yang dulu ia titipkan kepada ayah, ia minta hasil. Padahal dalam proses
perbaikan, ayah perlu banyak pengeluaran. Jika tidak mobil itu hanya laku
dijual ke tukang barang bekas. Mungkin ini pelampiasan ketidakterimaannya
menyekolahkanku.
Memang suatu kejanggalan jika aku
tercatat sebagai siswa baru sekolah bermutu. Keringat seorang tukang tambal ban
dan tukang gorengan terlalu jauh melampaui batas diri sendiri. Hanya melampaui
batas anggapan orang lain.
Ayah tak bisa diam membisu. Mobil
sudah ayah jual dan ia kembali berhutang dengan apa yang uwa pinta. Otomatis,
rumah yang ia singgahipun harus ayah tinggalkan.
Rintik tangis memuncak setelah
akhirnya ayah harus cabut malam itu juga. Detik itu juga. Ia pindah ke rumah
nenek dengan status menumpang dan merawat nenek. sungguh perjuangan yang
menyayat batin. Belum lagi terpaan badai jika aku sudah sekolah nanti. Jujur
aku tak terima ayah dibentak-bentak.
--- 0 ---
“Woy !” Bentak Andrian menggoyangkan
lenganku yang memegang pena di atas buku.
“Jangan melamun Bro!” Tambahnya.
Kukedipkan kata sekedar me-refresh
lamunanku.
“Nggak papa. Bagi seorang penulis
lamunan bisa jadi rupiah. “ Bantahku tersipu malu.
Andrian ikut duduk di lantai dua
asrama ini dengan bentangan pekuburan yang menghampar luas sejauh mata
memandang. Ia menyambung pembicaraan.
“Ke-li-ru-O-leh-Mu-tsa-qof” Sambil
telunjuknya menunjuk cerpen di majalah bulanan ke arahku, mengeja judul dan
pengarangnya.
“Hebat! tulisanmu dimuat di majalah
el-qudsy. Majalah terpopuler se-Solo Raya.“ Tangannya menepuk pundakku wujud
bangga kepada sobat karibnya.
“Proyek apa lagi nih yang kamu garap
?”tanyanya.
Kini lamunanku kabur dan menjelma
senyuman. Sobatku memang obat mujarab kepiluan.
“Syukurlah, nama penaku sedikit
menumpang di majalah. Ini yang pertama kalinya tulisanku dimuat. Cukup meniupkan
hawa semangat. Ini garapan novelku.” Jelasku.
“Ngomong-ngomong, kenapa kamu suka
menulis? Sebentar-sebentar, nulis. Di mana-mana, nulis. Kapan-kapan, nulis.
Kalau gak nulis, baca novel.” Tanyaku penasaran.
Aku memandang bentangan pepohonan di
samping asrama.
“Aku rasa ini sudah jadi passionku.
Dengan menulis, aku bisa menampung realitas dan imajinasi dalam bentuk karya
nyata dan bisa dinikmati. Syukur kalau bermanfaat bagi orang lain. Kalau sudah enjoy, jadilah hobby.” Jawabku.
“Lebih jelasnya, seperti kamu yang
suka main musik.” Tambahku.Andrian mengangguk faham.
“Tapi, apa kamu bisa bagi waktu
dengan tugasmu sebagai sekretaris OSIS? Tugas proposal ?”
Aku diam tertegun. Kucoba
menjawabnya.
“Sebenarnya aku kurang bisa. Tapi
akan aku usahkan.”
Aku terdiam sejenak.
“Oh, iya. Aku baru ingat.
Proposalnya belum aku sentuh sama sekali.”
Andrian mengingatkanku akan tugas
proposal dari ketua OSIS. Sudah dua hari ia menugaskanku. Aku cemas. Takutnya
ia menagih proposalnya.
“Pamit, ya. Aku ke kamar dulu.” Aku
meninggalkan jemuran dan menuju ke kamar dua, kamar seketaris. Dengan
berselimut kecemasan, aku meraih proposal dan menyalakan komputer OSIS.
“Assalamu’alaikum.” Seseorang
mengetuk pintu kamar.
“Wa’alaikum salam.” Jawabku.
Ternyata temanku, Maula, ketua OSIS.
Tangan kokohnya menyambut jemariku untuk bersalaman. Tampak wibawa seorang
ketua. Keringat dinginku meleleh.
“Gimana proposalnya, sudah sampai
mana?” Ia mengecek garapan proposalku di komputer.
“Belum kamu kerjain toh? “ Ia
heran ketika melihat halaman microsoft word yang masih polos.
“Baru
saja mau dikerjakan.” Jawabku pelan merasa bersalah.
“Jelas. Dari tadi kamu garap novel
terus. Kapan kerjanya?” Ia kesal dan menunjukan buku novel garapanku di samping
komputer.
“Maaf, saya lupa. Tapi saya siap
mengerjakannya.” Mukaku memerah.
“Masalahnya bukan kecil. Kalau
proposal belum jadi, acaranya akan molor terus. Belum lagi minta tanda tangan
kepala sekolah. Sampai kapan kamu lalai?” Sosok tegasnya muncul.
“Kasih saya kesempatan. Mulai saat
ini saya akan membagi waktu dengan baik. Saya bisa.” Ucapku meyakinkan.
“Ya sudah. Karena ini baru tugas
pertama , saya maafkan. Mungkin kamu belum terbiasa dengan tugas yang butuh
ketelitian dan waktu.” Ia masih menyimpan toleransi kepadaku walaupun guratan
kekesalan belum sirna di wajahnya.
“Kerjakan, ya !” Ia meninggalkan
kamar. Aku kembali dengan komputer.
“Santai Bro ! “ Sahut Andrian di
belakang punggungku. Rupanya bentakan keras Maula menyita perhatian dan tak sengaja
ia mendengarnya. Ia menyodorkan sesuatu dan menawarkannya.
“Makan getuk dulu aja !”
Keringat dinginku mengering. Sekedar
menenangkan ketegangan, aku makan kue tradisional Jawa itu. Rasanya yang manis,
mampu menggoyangkan lidah dan memberi ruang untuk sejenak berintrospeksi.
“Menjadi penulis memang butuh
manajemen waktu yang baik. Jangan sampai mengorbankan tugas.” Lirih Andrian.
“Ya, hobby itu hanya untuk
waktu luang. Setelah tugas tepatnya.” Jelasku, mengiyakan.
“Kok masih tegang, ada apa ? Melamun
lagi ya ?” Tanya Andrian keheranan mendapati guratan kesedihan di wajahku.
Aku merenung sejenak.
“Jejak luka memang terus
membayangiku. Cukup ayahku yang diinjak-injak. Biar nanti aku angkat derajat
dia di mata uwa.” Curhatku.
Aku mengangguk. Rupanya ia masih
ingat cerita yang pernah aku sampaikan.
“Memang itu sakit. Tapi gak boleh
menjadikan kamu nge-drop. Apalagi sampai lupa tugas. Cukup jadikan
dorongan bagi kamu untuk bisa memberi yang terbaik untuk ayahmu.”
“Terima kasih, Sobat. Semoga masa
depanku bisa memutar nasib ayahku.”
“Ya. Semoga masa depan kita semanis
getuk yang penuh warna dengan taburan kelapa parut putih yang gurih yang
menggiurkan lidah.” Ucap Andrian sambil memegang getuk dan menaburinya parutan
kepala. Kamipun kembali menikmatinya.
---

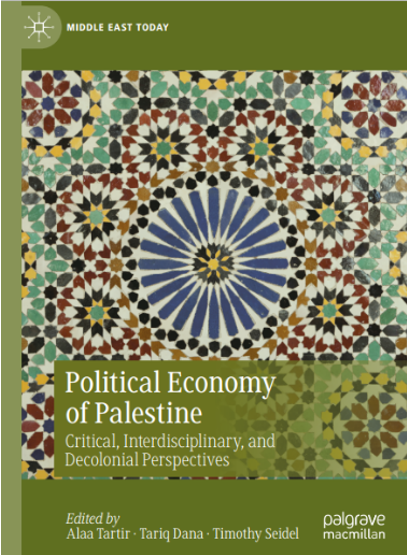


Penggambaran karakter anak nya menarik, alur cerita juga runtut. Tapi penjelasan tokoh ayah kurang detail, jadi emosi nya kurang dapet
ReplyDeleteThis comment has been removed by the author.
ReplyDeleteAlurnya nggak njrimet, tertata rapi. Lanjutkan Dan 👍👍👍
ReplyDelete